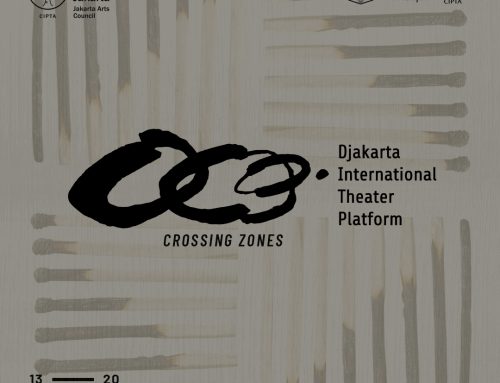Workshop Art Summit Indonesia: Toshiki Okada, 14-16 November 2016, Selasar Sunaryo Art Space, Bandung
Oleh Riyadhus Shalihin
Tubuh dan kata dalam tradisi teater yang ber-bahasa/teater bahasa, sering dikaitkan secara semena-mena dan langsung, pada ihwal transkripsi teks drama dan tubuh yang secara spontan mengkinetisasinya. Tanpa dilihat secara jelas apa yang tersimpan di dalam kata, dan apa yang secara laten dimaksudkan sebagai tubuh. Tradisi ini terutama diwariskan secara turun temurun dalam proses tak tuntas drama realisme, yang bersalah-sepakat untuk menjadikan kata sebagai kendali atas tubuh. Dimana tubuh harus dinaturalisasi pada bentuknya yang paling minimalistik, seadanya, sewajarnya, jika perlu benar-benar bersih, tak ada gerak yang sia-sia, lepas dari koordinat tekstualnya.
Tradisi linguistis yang salah pada proses ajar drama kata-kata, terutama pada kasus saduran teks realisme Eropa dan Amerika, menjadi cenderung mengedepankan usaha bercakap-cakap yang mengatasi salah ucap, dari ketidaktepatan antara logika dialog, dan tubuh yang berjalan bersama tuturan kalimat. Tubuh didisiplinkan dalam kultur aristokratik, dimana kata-kata menjadi juru bicara pikiran, oleh karenanya kata-kata menjadi pusat perjalanan komunikasi, sampai dan tidak sampainya maksud pikiran diujikan dalam medan kefasihan berbahasa lisan, sehingga yang lahir adalah dramaturgi para pendengar, bukan dramaturgi para penonton. Hal ini mengorientasikan tubuh sebagai anatomi sekunder dari pikiran yang diturunkan melalui panduan berbicara, tubuh dijauhkan dari ketidaksesuaian antara isi wicara dan gerak-gerik otomatisnya, tubuh harus berada di dalam kesatu-paduan leksikal, dari perpindahan setiap maksud paragraf yang diucapkan oleh aktor. Tidak ada ruang performance untuk kesalahan gerak, kegagapan wicara, ‘slip’ lidah (slip-tongue), ‘chaos’ keaktoran dari tidak terkelolanya antrian pikiran, dan tubuh yang tak bisa menguraikan satu persatu maksud ujaran dialog.
Pendisiplinan ini berupaya menciptakan aktor sebagai sesosok manusia yang kokoh berbahasa, sadar untuk mengeliminasi setiap cacat jeda antara maksud ucapan dan kosa gerak dari peran. Tubuh menjadi semakin klinis dan analitik terhadap setiap inchi ketidaksesuaian dari maksud kata, sebab kata telah merekam seluruh amatan pikiran, yang pada fase akutnya, tubuh akan mengalami krisis tuturan.
Panorama posisi tubuh dan kata dalam sejarah salah baca teater, yang coba saya tatapkan di awal, saya harapkan menjadi jalan masuk bagi kita untuk sama sama mendapatkan pengalaman menonton dan berada di dalam workshop penyutradaraan ‘Tubuh dan Kata’ dari Toshiki Okada, 14 sampai 16 November 2016, bertempat di Bale Handap Selasar Sunaryo Art Space, Bandung. Workshop yang diadakan dalam Art Summit Indonesia 8 (2016-2017), dengan tema ‘Reposisi : Membaca Kembali Peta dan Perubahan Dunia Seni Pertunjukan’. Toshiki yang merupakan pendiri dari Chelfitsch Theatre, bekerja dengan produk ‘tubuh’ dan ‘kata’ secara beriringan, baik sebagai sutradara, koreografer dan sastrawan. Bergegas dari nalar menulis (yang tekstual) dan penyutradaraan (yang tubuh) pada kerja Toshiki Okada, workshop ini perlahan-lahan berjalan di antara bayangan rezim bahasa, dan tubuh sebagai museum ingatan, berderap dengan pelan, menyiangi tirai teks yang hidup sebagai polisi gramatika di tubuh kita berabad lamanya.
Apa arti rumah bagi seorang aktor. Bagi saya yang terdidik sebagai penonton teater, rumah adalah menu umum dalam sajian tampil pertunjukan teater, terutama sekali dalam kategori drama realis, baik yang berlatar kultur Eropa/Amerika, dalam karya Henrik Ibsen, Tennessee Wiliiams hingga Sam Shepard, dan yang berlatar kultur Indonesia pada karya Umar Kayam, Kirdjomulyo ataupun Nasjah Jamin, dimana rumah seringkali menjadi pusat pengisahan, baik dalam interior artistik maupun interior konflik. Namun pertanyaannya adalah, dimanakah posisi ‘rumah’ secara lebih polos dan mentah, pada pengalaman sehari-hari para peserta workshop, di luar kostum dramatik para pengarang.
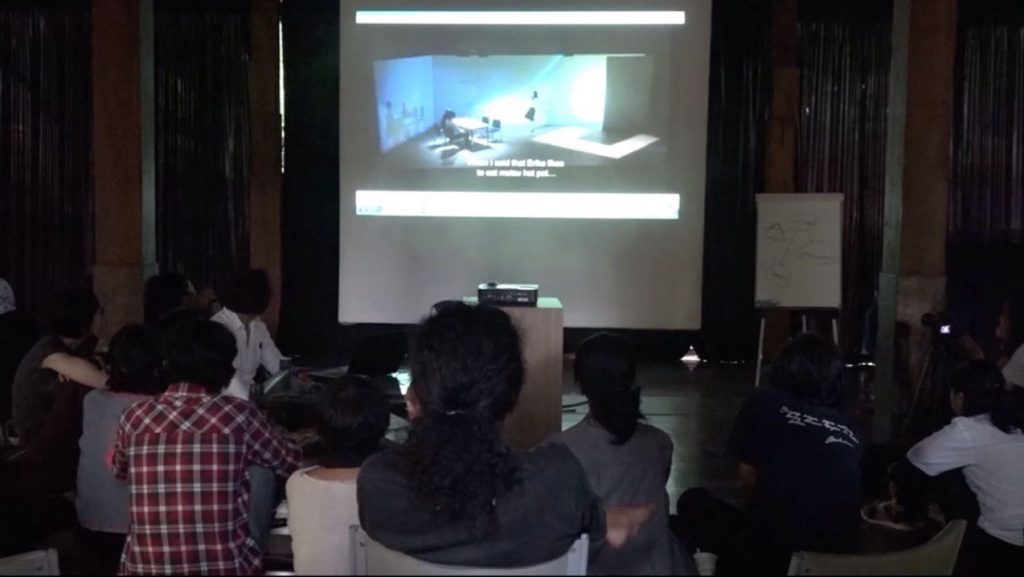
Ceritakan rumah anda, adalah kalimat instruktif workshop, yang menjadi kunci untuk membaca visi tubuh dan kata dalam kerja teater Toshiki Okada. Masing-masing dari peserta di area Bale Handap SSAS (Selasar Sunaryo Art Space) mengajukan tubuh dan ingatannya akan rumah, dari masing-masing presentasi, saya mencoba membagi beberapa kecenderungan ketinampilan presentatif para peserta, diantaranya yaitu : yang skematis, distraktif dan yang sadar koreografis. Presentasi skematis adalah tuturan yang jelas juga sangat rinci akan rumah sebagai detail teknis arsitektur, dan yang ditatap melalui sudut pandang tampak atas.
Abdi Karya, salah seorang peserta yang berasal dari Makassar, mendongengkan bahwa rumah dalam pengalamannya, adalah rumah yang menjaga hubungan keruangannya dengan binatang, dan membagi teritori etik menurut posisi gender, dalam artian tidak saling mensubordinasi. Pada rumah khas/adat yang masih asli, berada di Makassar, rumah selalu adalah rumah panggung yang memberikan ruang paling bawahnya (di bawah panggung) pada hewan ternak dan peliharaan pemilik rumah, artinya yang bukan manusia diberi posisi satu atap dalam bidang hunian secara bersama-sama. Juga rumah yang membuat dapur sebagai ruang ibu, dengan nalar memelihara dan merawat, memberi dan menumbuhkan, di mana seluruh kegiatan siklus hidup bermula dan berpulang ke dapur. Dapur juga menjadi ruang komunikasi yang lebih hidup ketimbang ruang depan yang dikuasai oleh kaum lelaki : bapa/ayah/pemuda, sebab segala informasi domestik yang mempribadi namun magnetis berkumpar di dapur, sehingga dapur menjadi tak lagi sebatas interior fungsi namun juga interior sosial. Dapur adalah kosmosis segala tradisi, kerukunan, ramalan, untung rugi perjodohan, yang baur berkelindan di antara panci, kompor, dan serakan kuali.
Masalahnya adalah dalam prinsip Toshiki Okada cerita tentang rumah, sekaligus juga gambar tentang rumah, yang dalam bahasa artistik khas miliknya, yaitu : ‘Image’, bukanlah rumah yang begitu licin dan mudah dipeta-ceritakan. Image bukanlah harafiah langsung gambar, dalam artian matra dimensional, image dalam bahasan Toshiki adalah gambar non-dimensi, yang lebih bersifat kelebat ingatan, tumbuh datang dan pergi, sifatnya samar-samar secara formal bangunan, namun kuat dalam fenomena seakan-akan ada, sehingga yang menyaksikan tuturan penampil terdorong untuk memiliki ikatan kepemilikan dengan seluk beluk kisah ruang. Image membuat gejala pengalaman, seakan penonton-pun pernah juga menghuni rumah yang sedang dituturkan.
Dalam kasus Abdi Karya, yang muncul adalah skematisasi atas rumah, peta teknis atas rumah, bukan ajakan untuk sama-sama menggenggam pengalaman akan rumah. Setelahnya, jika dirasa belum berhasil menguarkan afeksi ingatan, maka Toshiki akan menyuruh ulang para peserta untuk mengimaji-kan kembali rumah, yang bukan hanya dijelaskan secara gamblang lancar. Kebanyakan dari para peserta, pada akhirnya tetap tak bisa menembus dinding penjelasan atas rumah, dan tetap terkunci di dalam notulensi fisik bangunan, dengan berusaha lebih mendetailisasi per tempat, barang, dan setiap kelok sudut rumah. Usaha keras tersebut, justru menjadi lebih menertibkan ingatan, dan sekaligus membersihkan riak-riak atmosferitas-nya akan rumah. Bagi Toshiki, rumah sudah ada di dalam diri kita, bersama hadir, bahkan sejak lahir. Ketika terlalu keras dibayangkan bahwa rumah ada, maka image rumah akan hilang, karena rumah sudah ada, maka tidak usah dibayangkan dengan keras bahwa rumah ada.
Selain yang skematis, beberapa peserta juga menampilkan kecenderungan yang distraktif terhadap ingatannya atas rumah. John Heryanto, menunjukkan bahwa rumah baginya adalah entitas non-geografis, rumah bukan apa yang telah dan sedang ditempati, tetapi pada apa yang didatangi, bagi John rumah bukanlah kata benda tetapi kata sifat, wujudnya bukan taksa statis, tetapi anak kalimat yang terus belum selesai. Rumah bagi John adalah mencari dan menemui insting keingintahuan, sebagai alasan sebuah kepergian, yang tidak menjadi jawaban atas pertanyaan tentang pulang. Misal, dirinya pernah begitu penasaran dengan agama katolik, maka segera mungkin dia datangi sebuah kolese asrama calon biarawan-biarawati, dan meminta dibaptis serta menjalani hidup asketis, terpelanting dalam rutinitas keruhanian imamat. Tiba-tiba juga dirinya merasa terpanggil dalam jalan devosi budhisme, dan menetap di wihara, menjalani hidup ketat biksuni dan tinggal sebagai perapal ajaran kasunyatan Sidharta Gautama, namun juga dirinya pernah menggelandang di jalanan hidup sebagai seorang punkers (anak punk), hidup dari memungut sampah untuk makan, mengamen dan tidur tak tentu tempat. Hidup nomadik bukanlah kondisi yang disadari dan diinginkan, bagi John-keterlemparan dan terdamparnya tubuh, adalah rute tanpa rencana, dari satu faset ke faset berikutnya. Sejak kecil, dirinya sudah terbiasa dengan situasi tak tetap serta selalu berpindah, dimulai oleh ayah dan ibunya yang menitipkannya ke nenek, namun neneknya menitipkan John ke pamannya, dan pamannya menitipkan John ke sebuah pesantren-milik kerabatnya, dan di pesantren-karena John membutuhkan uang lebih untuk membeli makan/pakaian, dirinya memilih menetap di lokasi pembuangan sampah, dan menjadi pemulung untuk mengais untung.

Satu-satunya matra indrawi, yang membuat John rindu, dan merasa sedang di dalam rumah, adalah suara televisi dan radio. Sebab dimanapun John terdampar, gelombang audial dari kedua benda tersebut-lah yang selalu terngiang, dan terutama menemani John menjelang tidur, serta saat terbangun di keesokan hari. Kecenderungan distraktifis ini mulai terbaca, karena apa yang tertutur sebagai kisah dan dorongan tubuh yang tertatap oleh apresian, mengalami keterbelahan intensi, antara yang dikatakan dan yang ditubuhkan sama sama mengalami ke-tumpah-ruah-an, namun jebol di dua bendungan yang berbeda. Pada John, kakinya seperti selalu bergerak ke kiri dan ke kanan, condong bahunya pun terkadang membusung dan membungkuk, kedua kecenderungan kinetik ini seperti tidak memiliki lanskap kesepakatan dengan apa yang diceritakannya. Satu-satunya yang meng-sekunderisasi kisahnya adalah, tangan yang ingin menunjukkan arah kelok masing-masing tempat yang pernah mendamparkannya.
Bagi John sendiri, tubuh adalah medan primer yang tidak meminjam apapun, mengalami langsung dan menyampaikan pengalaman atas rumah, kata-kata adalah komunikasi sekunder, yang sudah biasa digunakan dan dipahami, namun kata-kata lacur seringkali mengatasi pengalaman akan rumah yang mewaktu di tubuh kita. Sedangkan bagi Toshiki, menangkap fenomena presentasi John, dirinya melihat hal tersebut sebagai surplus layer image, karena penonton mengalami dua setoran layer performance. Layer pertama adalah yang sensibisional, yaitu performatifitas tutur lisan dan tutur tubuh, yang terindrai sebagai aktivitas fisikal, tampak dan kongkrit, namun di luar yang lisan dan yang tubuh, muncul layer kedua, yaitu yang disposisional, adalah momen ketika keterbelahan pengisahan John, justru melahirkan bertubi-tubi dinding ephemeralitas rumah, dan tumbuh berbeda-beda di setiap proyeksi bayangan setiap apresian.
Pada presentasi dengan kecenderungan yang juga terbelah, Sugiyanti Ariyani, menempati rumah sebagai ruang huni dengan tubuh yang canggung dan ragu. Kisah yang ditawarkan bergerak dari rumah yang didefinisi sebagai organisme terberi, dan rumah yang terpola oleh rutinitas minat. Keterberian tersebut diurai dari posisinya, yang tertandai sebagai salah satu anggota anak-dari ayah dan ibu di dalam keluarganya, mau tak mau rumah sudah ada dan dipesan, bahkan sejak Sugiyanti di dalam kandungan. Rumah yang telah dipesankan tersebut, tidak begitu banyak memberikannya ruang pernyataan diri, dan jejaring istiadat di dalamnya mengikatkannya pada kestatisan tertentu. Sugiyanti mengkonstruk sendiri rumah kedua, yang dia formulasikan keadaannya berdasarkan sirkulasi kepadatan yang berlangsung sehari-hari, dan penataan ruang sepenuhnya berada dalam kendali ergonomi benda-benda kesayangan. Melalui rumah kedua atau kamar kost, Sugiyanti mendefinisi ulang persepsi tentang kepergian dan kepulangan, rumah pertama menjadi tempat wajib untuk dipulangi, sebagai seorang anak yang masih berada dan terikat dalam satu keluarga, sifatnya mutlak order absensi. Pada rumah yang kedua, sering tidaknya datang berada di dalam rumah tidak menjadi diameter kerasan dan tidak kerasannya Sugiyanti, sejarang apapun dirinya datang di rumah kedua, padanyalah dirinya merasa benar-benar pulang dan beristirahat. Jika rumah pertama menjadi tempat ‘pulang’ untuk pergi kembali, pada rumah kedua-lah segala kepergian benar-benar menemui halte keberhentiannya.
Bagi Toshiki Okada, melalui kasus Sugiyanti, suasana ruang dan cita-cita image dari dalam ingatannya, terasa sangat mempengaruhi arah hadap dan keseimbangan tubuhnya. Karena Sugiyanti membagi proyeksi rumah berdasar kata sifat, maka intensitas gestikular-nya berpendar di antara dua ruang, antara rumah administratif dan rumah keinginan bebas. Telapak kaki Sugiyanti seperti berusaha bergoyang dan bergegas dari kiri dan kanan, dari arah pijak kaki yang bertumpu di depan dan belakang, seperti ada selalu hadir dua ruang berbeda yang membayangi arena ucap tubuhnya. Namun ketika Sugiyanti benar-benar diam, Toshiki merasa ruang imajis atas rumah, seakan jebol, membludak dan membanjiri bayangan apresian atas rumah. Baginya ada kecenderungan, ketika tubuh benar-benar diam, namun segala intensi kita atas ingatan rumah menyedot habis energi tubuh, maka ruang akan muncul, imagenya lahir. Namun ketika tubuh berusaha memberi ukuran atau memberi penjelasan spesifik atas rumah, maka image atas rumah cenderung tertahan.

Image memiliki nalar bertuturnya sendiri, tempo dan juga geraknya sendiri. Image-lah, yang menggerakan tubuh, tidak didesain, sifatnya tanpa penyutradaraan si aktor, tidak disengaja, dan tak terduga. Hasilnya yang paling kentara adalah ketidaksesuaian, selisih, jeda, renggang, keterlambatan derap antara produksi kata yang diucapkan dan produksi gerak tubuh. Namun ketidaksesuaian itu bukanlah visi visual, atau visi koreografis, sebab akan terasa image yang diskematisasi dan image yang menggelontor begitu saja. image sudah ada, sebelum masuk panggung, tugas aktor hanyalah memindahkan dunia image ke dalam panggung, dan aktor hidup di dunia image-nya sendiri, mengelola energi pasrah terhadap image.