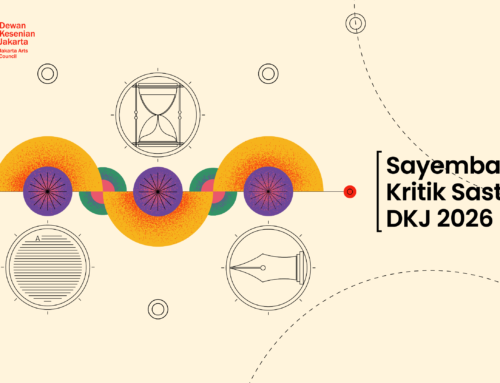Sepekan telah lewat Indonesia kehilangan seorang Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Sosok negarawan, politikus dan berbagai predikat lain yang melekat padanya, termasuk gelar “Bapak Pluralisme” sebagaimana disebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada upacara pemakamannya di Jombang, Jawa Timur, penghujung Desember lalu.
Terlepas dari hingar-bingar dan berbagai kontroversi dalam dunia perpolitikan di tanah air, Gus Dur sejatinya merupakan sosok multidimensi. Pada usia belasan tahun Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel dan buku-buku yang tidak sekedar cerita cerita silat dan fiksi, akan tetapi wacana tentang filsafat dan dokumen-dokumen mancanegara tidak luput dari perhatianya. Selain membaca, Gus Dur gemar pula bermain bola dan musik. Maka tidak heran jika Gus Dur pernah menjadi komentator sepak bola di televisi dan menjadi kolumnis sepakbola pada sebuah majalah. Menonton bioskop juga ikut melengkapi hobinya hingga menimbulkan apresiasi yang mendalam terhadap dunia film. Bahkan pada 1986-1987 Gus Dur terlibat sebagai juri Festival Film Indonesia.
Sisi lain Gus Dur yang tidak cukup banyak disinggung barangkali kedekatannya dengan dunia kesenian dan kebudayaan. Alih-alih menjadi ulama selepas mengecap pendidikan di Mesir dan Irak, Gus Dur justru lebih terkenal sebagai budayawan sekembalinya di tanah air. Pada akhir periode tahun 1970-an, Gus Dur beberapa kali terlibat mengisi ceramah-ceramah kesenian dan kebudayaan, termasuk di lingkungan Taman Ismail Marzuki yang pada masa-masa itu tengah mengalami periode keemasannya sebagai sentral aktivitas kesenian dan kebudayaan.
Pada Juni 1975 ceramah Gus Dur bertajuk “Kebudayaan Arab dan Islam” bahkan membuat banyak hadirin yang memenuhi Teater Arena, Taman Ismail Marzuki terhenyak. Dalam ceramahnya itu Gus Dur menyinggung persoalan sensitif menyangkut kegagapan masyarakat Indonesia yang mengidentifikasikan kebudayaan Arab sama dengan Kebudayaan Islam.
“Diktum Arab adalah Islam, yang seringkali berakibat Islam adalah Arab, menjadi semacam rangka berpemikiran yang telah membuat kita bersikap tidak realitas selama ini. Sudah waktunya cara memandang semacam ini diubah, dengan cara menyadari sepenuhnya akan besarnya diversifikasi unsur-unsur kebudayaan Arab, sebagaimana yang juga dimiliki oleh kebudayaan bangsa kita sendiri”, kata Gus Dur menutup ceramahnya.
Kontroversi kembali menyapa Gus Dur saat terpilih sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta, DKJ periode 1982 – 1985. Geger di kalangan nadhiyin yang mempertanyakan kadar kesenimanan Gus Dur yang pada saat itu sekaligus menjabat Ketua PB Nadhatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Namun pertanyaan serupa justru tidak muncul di kalangan seniman. Toeti Heraty Noerhadi, sastrawan, yang sama-sama menjabat Ketua DKJ bersama Gus Dur pada periode itu malah memiliki kesan mendalam dengan kehadiran Gus Dur di lembaga yang keberadaannya diprakarsai Gubernur Jakarta Ali Sadikin itu.
“Masa-masa itu paling mengasyikkan, dimana kami sering berdiskusi, bertukar pikiran tentang berkesenian dan mengenai perlunya seniman memiliki kebebasan dalam berekspresi. Tentu tidak melulu serius, karena diselingi dengan joke-joke-nya yang segar”, katanya mengenang.
Sayang, kata Toeti, kehadiran Gus Dur di DKJ hanya berlangsung singkat karena kesibukan Gus Dur yang pada saat itu mulai merambah ke dunia politik. Namun bagi Toeti, meski tidak sampai penuh tiga tahun menjabat di DKJ, kehadiran Gus Dur dengan latar belakang keilmuan dan wawasannya yang luas telah memberi warna lain bagi DKJ.
Selamat jalan Gus Dur …