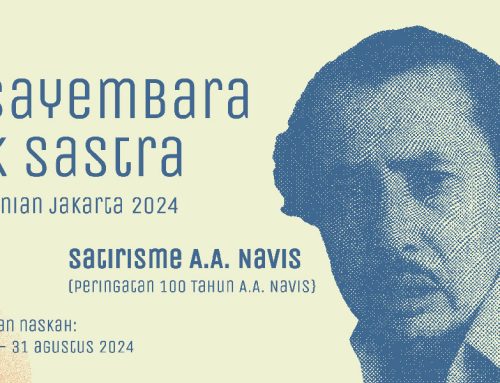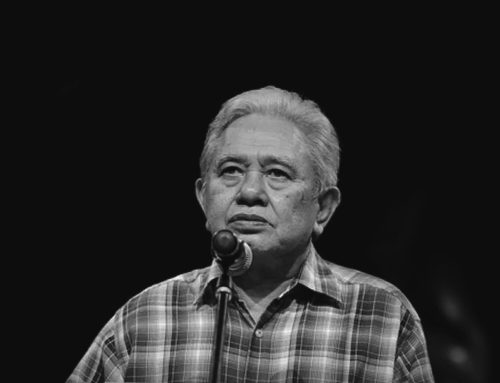Kritik sastra sesungguhnya—dan seadilnya—mesti ditempatkan sebagai kajian yang memusatkan diri pada karya sastra tertentu. Kami tekankan frase “memusatkan diri” sebab suatu telaah tidak bisa disebut kritik sastra bila ia hanya berputar-putar di luar—misalnya saja sibuk dengan riwayat hidup pengarang, sejarah sastra, atau sosiologi—tanpa berani membenturkan diri ke dalam pokok karya sastra yang hendak dibahasnya. Apa pun pendekatannya, seorang penulis kritik sastra harus menyatakan visinya sendiri tentang karya yang dihadapinya dengan jernih dan tajam. Adapun sebuah karya sastra tidak lahir dalam kekosongan: ia “berutang” kepada lingkungan yang mendorong kelahirannya; namun, bersamaan dengan itu, sebuah karya sastra mengandung kekhasannya, membedakan diri dari karya sastra lain yang lahir dari konteks yang serupa. Kritik sastra bukan hanya menangkap kekhasan ini, namun juga menerjemahkannya menjadi suara lain yang belum disadari oleh penulis sastra yang bersangkutan.
Dalam pendekatan sastra yang “murni”, misalnya yang dibangun oleh Rene Wellek dan Austin Warren, pemahaman dan penilaian karya sastra tetap harus ditempatkan dalam konteks yang ada di luar dirinya, yaitu norma-norma sastra yang berlaku di sepanjang sejarah sastra. Dengan itu terlihatlah bukan hanya pengaruh karya-karya sastra terdahulu, melainkan juga kebaruan-kebaruan karya yang dimaksud beserta kemungkinan umpan baliknya terhadap sejarah sastra dan norma-norma sastranya.
Dalam pendekatan strukturalis yang memusatkan perhatian pada apa yang dinamakan kaidah sastra, poetika, yang setara dengan apa yang dinamakan langue di dalam kajian linguistik, kekhasan karya sastra yang setara dengan apa yang disebut parole, pun tidak diabaikan. Hampir semua kajian strukturalis mengenai kaidah yang bersifat umum, kolektif, abstrak, berangkat dari kajian yang rinci mengenai karya sastra tertentu. Demikianlah Roland Barthes, misalnya, membedakan karya sastra yang writerly dari yang readerly.
Dalam pendekatan sosiologis seperti strukturalisme genetik Lucien Goldmann misalnya, terdapat pembedaan antara karya sastra yang mayor dengan yang minor, yang bersifat sosiologis-filosofis dengan yang semata psikologis, libidinal. Terry Eagleton mengatakan bahwa karya sastra tidak sekadar reproduksi yang pasif dari ideologi, melainkan reproduksi yang aktif dan kreatif, yang ikut membentuk ideologi itu. Kajian pasca-kolonial yang dilakukan Sarah Upstone terhadap karya-karya Salman Rushdie, Toni Morrison, dan Wilson Harris, memperlihatkan bagaimana karya-karya ketiga pengarang tersebut telah memberikan kekhasan masing-masing dalam menjawab persoalan keruangan warisan kolonial dan usaha-usaha pembebasan daripadanya.
Dengan menimbang berbagai pendekatan di atas, kami bisa menyatakan bahwa penilaian kami terhadap karya-karya kritik sastra yang menjadi peserta di dalam sayembara ini berdasarkan pertama-tama dan terutama pada adanya pemusatan perhatian terhadap karya sastra tertentu. Akan tetapi, deskripsi dan analisis terhadap karya sastra belaka dipandang tidak mencukupi untuk menjadi sandaran dalam menentukan keistimewaan sebuah karya kritik sastra. Kemampuan sebuah karya kritik dalam mempertautkan karya sastra yang bersangkutan dalam berbagai kemungkinan konteks secara proporsional dan dalam membangun argumen secara tekstual menjadi sangat penting bagi kami. Bersamaan dengan itu, penulisan yang jernih dan ketat, dan retorika yang menarik, akan membuat sebuah karya kritik sastra mampu mengungkapkan kekuatan, kekayaan, kelebihan dan kekurangan karya sastra yang dibahasnya.
Terdapat 69 (enam puluh sembilan) naskah yang memenuhi syarat administratif, yang kami baca secara “buta”, yaitu kami baca tanpa nama pengarang masing-masing. Kecenderungan umum yang segera tertangkap dari sejumlah makalah tersebut adalah adanya kecenderungan untuk menggunakan teori. Hanya saja, sebagian besar dari karya-karya kritik yang demikian memperlihatkan “ambisi teoretik” yang terlalu berat, yang justru membenamkan karya-karya sastra yang bersangkutan. Ada juga yang cenderung menampilkan “teori” sebagai tidak lebih dari parade kutipan-kutipan yang sangat tidak sebanding dengan temuan mengenai karya-karya sastra yang bersangkutan. Di lain pihak, terdapat beberapa karya kritik sastra yang cenderung lugu, tanpa dukungan teoretik yang memadai. Sebagian karya-karya kritik yang demikian terperangkap pada parafrase belaka atas karya-karya yang dibicarakan atau bahkan menjadi semacam sinopsis yang berkepanjangan, tanpa memberikan analisis yang memadai.
Kecenderungan lainnya yang muncul adalah karya-karya kritik sastra yang tampaknya berasal dari tugas-tugas kuliah dan bahkan menyerupai sebuah karya skripsi atau tesis yang lengkap. Kelemahan karya-karya yang demikian adalah sifat resminya, yang membuat karya-karya yang dibahas seakan menjadi objek yang mati, sementara pembahasannya sendiri menjadi pucat dan membosankan. Kecenderungan terakhir yang tertangkap oleh kami adalah pengaruh yang kuat dari pendekatan yang dinamakan kajian budaya, yang menempatkan kajian mengenai konteks sosial dan politik terlalu dominan, cenderung abai pada telaah mengenai teks: kontekstualisasi tersebut menjadi ulasan yang berdiri sendiri, lepas dari karya sastra yang dibahas.
Dari seluruh karya kritik sastra yang disebutkan di atas, kami menemukan enam buah karya kritik sastra yang setidaknya secara relatif dapat dianggap sebagai karya-karya yang “terbaik”. Tiga yang pertama adalah para Pemenang Harapan, yang diumumkan tanpa peringkat, yaitu naskah-naskah dengan nomor-nomor 56, 60 dan 08. Tiga yang berikutnya adalah Pemenang Ketiga (naskah nomor 54), Pemenang Kedua (naskah nomor 61), Pemenang Pertama (naskah nomor 31).
Naskah nomor 56, “Oh, Roman (Bukan) Picisan”. Karya kritik sastra ini membahas novel Djokolelono yang berjudul Setan van Oyot (2019) dalam perspektif sejarah kolonial, terutama yang terkait dengan pabrik gula. Si pengulas, dengan pengetahuan sejarah dan kebudayaan yang lumayan luas, akhirnya mengungkapkan dengan meyakinkan bahwa karya yang dibahasnya itu bukanlah karya picisan, karya populer yang tidak berharga atau yang “dilecehkan” dalam pengertian Ariel Heryanto, melainkan sebuah karya yang serius, yang layak disebut novel sejarah. Di balik pencantuman istilah “roman picisan” pada sampul novel, justru terdapatlah sebuah kontras yang dibuat oleh si pengarang sendiri: novel ini menggambarkan hubungan sosial yang pelik dalam masyarakat di wilayah tertentu pada dekade-dekade sebelum kemerdekaan. Pengulas menunjukkan bahwa dengan bentuk narasi yang biasa dan “populer”, pengarang cukup berhasil menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh setiap tokoh cerita, berikut rincian latar sejarah yang kaya.
Kelemahan naskah “Oh, Roman (Bukan) Picisan” adalah bahwa ia tidak memperlihatkan perspektif baru dalam pengkajian karya sastra populer yang disebut picisan itu. Sudah banyak studi terdahulu yang menyingkapkan bahwa nilai sebuah karya populer bukanlah terletak pada aspek estetiknya, melainkan aspek sosiologisnya. Pembahasan aspek estetik untuk menyatakan novel termaksud sebagai roman yang tak picisan sangat jauh dari memadai.
Naskah nomor 60, “Novel Eksploratif tanpa Tendensi Membuka Ruang Eksperimen”. Karya kritik ini kuat dalam ulasannya yang bersifat formalistik, yang mengikuti kaidah-kaidah sastra yang bisa dikatakan konvensional seperti alur, karakter, teknik naratif, imaji, dan makna atau tema. Ulasan terhadap Surti + Tiga Sawunggaling karya Goenawan Mohamad yang terbit pada tahun 2018 tersebut disampaikan dalam penuturan yang sangat lancar, dengan peralihan-peralihan yang mulus. Selain itu, meski hanya dengan selintas, pembahasan juga dilakukan secara kontekstual, yaitu bahwa kekuatan tekstual ditempatkan dalam konteks generik dan sekaligus sejarah sastra seperti yang antara lain disarankan oleh Rene Wellek dan kaum strukturalis. Tampak dalam hal ini penulis kritik memperlihatkan pengetahuan yang baik mengenai perkembangan atau sejarah sastra Indonesia dengan mengacu kepada beberapa karya yang dianggap “kanonik”. Pengulas berhasil menunjukkan bahwa aspek puitik tersebut adalah kekuatan utama novel ini, yaitu dengan jalan mengolah plot spiral yang berpusat pada tokoh utamanya, seorang perempuan bernama Surti yang berada di tengah pergolakan revolusi setelah kemerdekaan.
Pengulas memberikan penilaian yang baik terhadap kemampuan Goenawan Mohamad untuk tidak terperangkap dalam kecenderungan melahirkan karya yang terlalu bersifat politis, yang menurutnya sudah basi. Selain itu, karya kritik ini juga ternyata menggunakan pendekatan estetik konvensional karena usahanya untuk menyesuaikan pada kecenderungan Surti + Tiga Sawunggaling itu sendiri. Dengan kata lain, penulis kritik ini mencoba memberikan apresiasi dan kritik terhadap karya yang dibahas sesuai dengan kekuatan yang terkandung dalam karya itu sendiri. Ia sendiri mengharap bahwa penulis sekelas Goenawan memberikan kekuatan yang lebih dari sekadar kekuatan estetik yang formalistik di atas.
Kelemahan karya ini, menurut kami, terletak pada dua hal, yaitu dalam pembahasannya mengenai kondisi kritik sastra di Indonesia yang menurut kami tidak fungsional dalam pemahaman terhadap teks yang ia bahas, menjadi semacam sekadar digresi, dan mengenai konsep realisme magis yang ia gunakan. Seperti yang ia harapkan dari Surti + Tiga Sawunggaling, kami sebenarnya berharap ia dapat menempatkan karya tersebut ke dalam konteks yang lebih luas dan beragam daripada sekadar konteks estetik.
Naskah nomor 08, “Menelusuri Abjeksi dan Maternal Passion dalam Buku Puisi Ibu Mendulang Anak Berlari Karya Cyntha Hariadi”. Karya kritik ini sadar dengan teori dan mengemukakannya secara eksplisit: teori abjeksi dan maternal passion dari Julia Kristeva. Kekuatannya terletak pada ketepatan pemilihan kerangka konseptual tersebut untuk mengungkapkan kekuatan puisi yang dibahasnya. Teorinya menjadi tidak terasa dipaksakan, melainkan justru sangat membantu orang dalam membaca dan memahami semua yang seakan berlangsung begitu saja di dalam puisi. Pengulas memusatkan telaahnya pada pengalaman perempuan, khususnya ibu, yang terkait dengan rasa takut, cemas, fantasi, cinta dan benci dan bahkan alienasi. Selain itu juga diulas perihal maternal passion, yaitu “hasrat atau gairah tak terkendali yang berada
Yang juga menjadi kekuatan karya kritik ini adalah kontekstualisasinya, yaitu penggambaran sosiologis mengenai peran ibu di dalam masyarakat dan juga dalam karya-karya sastra sebelumnya. Gambaran tersebut memang sudah menjadi pengetahuan umum yang bahkan bisa dikatakan basi. Akan tetapi, dengan dihadapkan dengan puisi Cyntha Hariadi yang terbit pada tahun 2016 tersebut, konteks itu menjadi segar dan nyata kembali. Dengan kata lain, karya kritik ini berhasil membangun hubungan dialektik antara teks dengan konteks.
Kelemahan karya kritik ini terutama, menurut kami, terletak pada paparannya mengenai pengertian puisi. Berbagai kutipan teori puisi dikemukakan hanya untuk sampai pada kesimpulan bahwa puisi itu bersifat personal dan jujur, pengertian yang sangat basi dan memubazirkan teori Kristeva yang digunakan. Andaikata si pengulas mengambil konsep yang lain tentang puisi, misalnya konsep mengenai retorikanya, yang dapat membuat pengalaman keibuan dapat digambarkan secara efektif, karya kritik ini akan menjadi lebih kuat.
Naskah no 54, “Pikat ‘Lama’, Siasat ‘Baru’”, adalah Pemenang Ketiga. Tidak ada paparan teori yang eksplisit di dalam karya kritik ini. Meskipun demikian, dari caranya dalam melakukan deskripsi dan penjelasan, terbayang satu perspektif yang berbau pascakolonial. Naskah ini membahas kumpulan puisi karya Heru Joni Putra yang berjudul Badrul Mustafa, Badrul Mustafa, Badrul Mustafa (2017). Karena puisi-puisi tersebut banyak menggunakan pepatah-pepatah sebagai bahannya, penulis kritik ini menempatkannya ke dalam konteks khazanah pepatah tradisional Melayu, khususnya Minangkabau. Yang segera memikat dari kontekstualisasi ini adalah penguasaan data si kritikus mengenai sejarah panjang perlakuan masyarakat Indonesia sejak masa kolonial hingga tahun 1950-an dan bahkan sampai sekarang terhadap pepatah, pantun, atau bentuk-bentuk sastra tradisional lainnya. Penulis kritik ini dengan rinci menggambarkan dengan kritis bagaimana masyarakat sastra Indonesia cenderung berusaha menyangkal dan meninggalkan berbagai format sastra lama itu di satu pihak, tapi terus menggunakannya di pihak lain. Dalam hal ini, pengritik sekaligus menempatkan pepatah-pepatah itu dalam perspektif budaya populer, yaitu pengetahuan dan kebijakan serta juga kekuatan retorik lokal. Sang penyair menggubah puisinya sembari mempertahankan jejak-jejak pola pantun untuk memberi makna yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan makna aslinya.
Bagi si pengulas, karya Heru Joni Putra menjadi bermakna karena ia terbebas dari sekaligus dua kecenderungan yang bertentangan di atas, yaitu penyangkalan terhadap dan sekaligus pengakuan akan kekuatan pepatah-pepatah itu. Dalam konteks perkembangan sejarah sastra Indonesia, apa yang disumbangkan oleh Badrul Mustafa, Badrul Mustafa, Badrul Mustafa, menurutnya, adalah sebuah kiat baru dalam menyiasati pepatah di atas, yakni “mengingat”, “mengubah” dan “membantah”, yang mengingatkan pada konsep ruang ketiga atau liminal dari Homi Bhaba. Kiat baru tersebut, oleh kritikus itu, dibuktikan dengan pemberian bukti-bukti tekstual yang relatif rinci.
Kelemahan karya kritik ini terutama justru terletak pada satuan-satuan konsep dalam kiat tersebut. Satuan-satuan konsep itu tidak ia gunakan untuk memilah dan menganalisis karya-karya puisi yang dibahas. Artinya, pembaca tidak memperoleh pemahaman yang baik mengenai mana yang mengingat, mana yang mengubah, dan mana yang membantah.
Naskah nomor 61, “Membaca Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi Melalui Genre Coming of Age”, adalah Pemenang Kedua. Karya kritik ini memperlihatkan kekuatan utamanya pada analisis terhadap novel Yusi Avianto Pareanom yang terbit pada tahun 2016 itu dengan menggunakan kaidah genre coming of age yang, menurutnya, menjadi pilihan penulis karya sastranya sendiri, sebagai semacam premis utama. Yaitu sejauh mana tokoh utama dalam novel gagal atau berhasil melewati proses dari keremajaan menuju kedewasaan. Kekuatan lainnya adalah penguasaan si kritikus terhadap karya-karya lain yang sejenis, baik yang ada dalam khazanah sastra Indonesia maupun sastra Barat. Karya ini juga memberikan sanggahan yang masuk akal terhadap kajian-kajian terdahulu terhadap karya sastra yang sama, yang dengan demikian, menunjukkan keseriusannya dalam kajian kritisnya.
Satu hal penting yang menjadi temuan kritik ini adalah bahwa Raden Mandasia si Pencuri Daging Sapi terlalu sederhana, naif, dalam mengikuti kaidah genre yang digunakan. Apa yang ia namakan sebagai pilihan politis sastrawan ini, yaitu menjadikan tokoh cerita sebagai anak yang seakan tidak pernah dewasa, bergantung pada orang-orang yang lebih dewasa, merupakan sebuah pilihan yang disesali oleh si kritikus. Pengritik memaparkan berbagai pengalaman dan peristiwa yang dialami tokoh utamanya termasuk berbagai kekerasan yang brutal dan peperangan yang kejam dan pengalaman seksual yang fantastik. Tapi ternyata tak terjadi guncangan atau krisis pada diri sang tokoh. Seakan semua risiko itu ditinggalkan begitu saja oleh pengarang. Artinya, novel ini tidak berhasil mengolah tema coming of age yang telah dipilihnya sendiri.
Kelemahan karya kritik sastra ini adalah fokusnya yang terlalu besar pada konteks genre sehingga ia tidak bisa membayangkan hubungan antara teks sastranya sendiri dengan berbagai kekuatan diskursif yang lain, yang ada di luar genre itu. Padahal, “pilihan politis” sang novelis seperti sudah dikemukakan membuka pertanyaan yang dapat membawa kepada kemungkinan paparan yang lebih komprehensif.
Naskah nomor 31, “Bualan Warto Kemplung, Cerita Bersambung Mustofa Abdul Wahab”, adalah Pemenang Pertama. Karya kritik sastra ini menyoroti strategi dan bentuk naratif novel Dawuk: Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu karya Mahfud Ikhwan (2017), dengan fokus sudut pandang penceritaan oleh dua narator. Pengulas menunjukkan bahwa peristiwa pembacaan adalah upaya untuk memasuki suatu narasi sekaligus proses untuk memahami bagaimana “realitas” terbentuk dalam narasi, baik narasi versi narator pertama maupun yang kedua. Masing-masing versi saling berkelindan sehingga pembaca digiring agar tidak lagi mempersoalkan “realitas” mana yang lebih mungkin untuk dipercayai. Analisis naratologisnya tidak hanya mengungkapkan kepiawan dan kebaruan estetik dari karya yang dikritik, melainkan juga membuatnya berhasil mengungkapkan posisi pasca-kolonial dan pasca-modern karya tersebut sebagai karya yang melawan lupa, menjadi penulisan sejarah alternatif dari sejarah resmi, dan sekaligus sebuah karya yang sadar-diri atau metafiksi.
Kekuatannya yang lain adalah kemampuan karya kritik ini menerapkan berbagai teori yang menjadi dasar perspektifnya dengan sangat cermat tanpa membuat teksnya mengalami penindasan. Karya kritik ini memperlakukan teori secara terbuka dan membiarkannya membangun hubungan dialektik dengan teks sehingga ia berhasil mengungkap kebaruan karya yang diteliti dan sekaligus menemukan kontribusi karya terhadap kerangka teori yang ada. Kemampuan kritik ini dalam menempatkan Dawuk dalam konteks sejarah sastra Indonesia dan bahkan dunia adalah kekuatan lainnya yang patut digarisbawahi. Hal itu tidak hanya menunjukkan bahwa sang penulis mempunyai wawasan sejarah sastra yang memadai, melainkan juga memperlihatkan kemampuannya menggunakan wawasan tersebut dengan tepat.
Akhirnya kami harus menyatakan bahwa pemeringkatan dan pemenangan yang kami putuskan di atas mengikatkan diri sepenuhnya kepada lingkup 69 naskah yang kami baca. Keenam naskah itu menjadi yang terbaik hanya jika terbandingkan dengan naskah-naskah yang lain yang masuk ke dalam Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta 2019 ini belaka. Bagi kami, keenamnya, tanpa kecuali, masih harus berjuang keras untuk menjadi karya kritik sastra yang unggul, yang bisa berdiri kokoh di khazanah sastra Indonesia. Dengan kata lain, keenamnya masih harus ditulis ulang dengan cermat dan disunting dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebulatan argumen, ketajaman kupasan, kelancaran bertutur, kepiawaian berbahasa dan kewibawaan kritik sastra.
Demikianlah penilaian kami.
Dewan Juri:
Faruk
Nirwan Dewanto
Wicaksono Adi