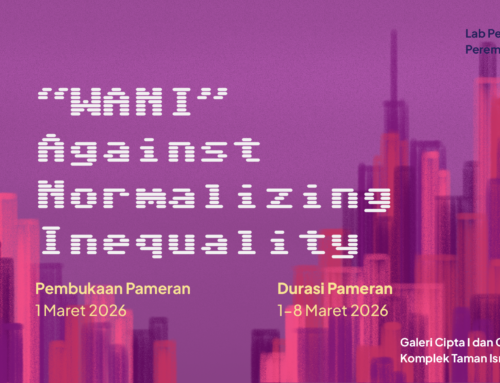Oleh Rira Nurmaida
“No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main.” —John Donne
Sejarah yang secara etimologis berakar pada syajaratun yakni pohon dalam bahasa arab, bisa dikatakan sebagai catatan dari akar ke pucuk mengenai perubahan, pergantian masa, peristiwa, pengalaman yang terkadang tidak secara kasat mata memiliki hubungan kausal dengan pengalaman kita hari ini. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu, pencatatan sejarah tidak pernah lengkap, bisa dianggap seperti upaya penyusunan teka-teki gambar dengan banyak kepingan yang hilang. Hal tersebut nyaris tak bisa dihindari. Belum lagi lensa yang digunakan pun beragam dengan sudut pandang yang menitikberatkan pada elemen-elemen yang paling menarik hati atau dianggap paling berpengaruh oleh penulisnya. Dengan kesadaran ini, pandangan kritis harus senantiasa menyertai pembacaan terhadap berbagai versi sejarah yang ada.
Meski demikian, tentu sah-sah saja jika kita berharap ada metode yang cukup adil, katakanlah demikian, dalam menuliskan sejarah sehingga pembacaan kita hari ini akan memberi gambaran yang paling mendekati kenyataan kontemporernya dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan tuntutan atas objektivitas dari rasionalisme, namun lebih menjanjikan kiranya jika dapat memperbanyak unsur subjektif yang memperkaya catatan sejarah tersebut. Pencarian semacam itu juga tak luput dalam aspek sejarah seni rupa Indonesia.
Sepanjang penuturan materi lokakarya historiografi seni rupa Indonesia 23 November 2025 lalu, Aminudin TH Siregar mengajak untuk menilik sejumlah penulisan sejarah seni dari daratan Eropa, ke Asia Kecil, juga wilayah Timur Tengah sebelum akhirnya memusatkan perhatian untuk meninjau upaya pencatatan sejarah seni rupa Indonesia. Nama Vasari sering disebut sebagai salah satu penulis sejarah seni awal dalam banyak teks sejarah seni. Lebih tepatnya, Vasari adalah pemuka dalam penulisan individual cult para seniman Italia khususnya di Florence. Ia bercerita banyak tentang kehidupan mereka yang digambarkan sebagai sosok genius yang hadir secara ajaib di muka bumi. Berikutnya disebut pula Winckelmann, seorang kolektor barang antik yang dianggap Bapak Sejarah Seni karena mulai mendeskripsikan dan membuat kategori gaya karya seni dari berbagai artefak yang ia dapati, terutama melalui program-program Grand Tour-nya.
Ada juga Riegl yang mulai melepaskan diri dari Eropa sebagai pusat dan melebur batas seni tinggi-seni rendah, atau formalisme yang digagas Fry, maupun gambaran sejarah seni di Turki dalam tulisan Toprak, dan lain sebagainya yang masing-masing memberikan pendekatan berbeda dalam penulisan sejarah seni rupa. Adapun Claire Holt menjadi sorotan berikutnya dan dibahas lebih dalam karena pendekatannya yang menarik yang membahas seni di Indonesia dengan tajam, detail, sekaligus akrab. Holt merupakan seseorang yang melihat dari luar sekaligus dari dalam. Dia melakukan banyak riset lapangan berkeliling ke candi, museum, maupun sanggar dan kampus dan berinteraksi langsung dengan pelaku seni tradisional maupun modern Indonesia selain memeriksa arsip dan dokumen untuk membuat gambaran seni di Indonesia terutama pasca Perang Dunia Kedua.
Keindonesiaan atau spirit Indonesia dalam seni rupa
Unsur yang menarik dalam membahas seni rupa Indonesia adalah terma Indonesia itu sendiri. Sebuah kesatuan yang majemuk dengan unsur budaya yang begitu berbeda satu sama lain namun disatukan oleh cita-cita politik menjadi suatu negara. Karya seni bagaimana yang merepresentasikannya? Atau apakah ada kesinambungan dalam karya seni yang lahir di sini atau dari benak dan tangan mereka yang menjadi bagian dari Indonesia? Bagaimana menggambarkan perjalanan kehidupan berkesenian di Indonesia? Di manakah tempatnya dalam percaturan seni rupa dunia?
Fenomena Indonesia yang multikultural ini menjadi tantangan yang tidak mudah. Lini masa seni rupa tidak linear di sini, pembabakan sulit dipisah dengan garis tegas untuk dibedakan melalui gaya dan semacamnya. Ada vakum panjang dalam seni patung dari masa kejayaan saat banyak candi dibangun dengan masa Hindia Belanda misalnya, sehingga Raffles menulis dalam laporannya sebagai forgotten skill. Sedangkan pada masa modern, dalam kurun waktu yang sama bisa ditemukan gaya berbeda dalam teknik lukis di Indonesia, contohnya gaya geometris abstrak yang dipraktikkan Sadali yang hadir bersamaan dengan realisme ala Sudjojono. Gaya tidak bekerja sebagai musim di sini. Perkembangan estetis pada satu individu seniman saja tidak bergerak lurus, kadang sirkular, spiral, atau bolak-balik dan berbelit. Bahkan Claire Holt pernah menyatakan bahwa observasi seni rupa di Indonesia membutuhkan lensa multifaset, sudut pandang antropologi, sosiologi, filsafat, psikologi, etnografi, dibutuhkan untuk mencernanya.
Pada hasil penelitiannya yang diterbitkan sebagai buku “Art in Indonesia, Continuities and Change”, Claire Holt menarik benang merah terkait tema berulang yang dieksplorasi dalam berbagai bentuk dan konteks, yakni perihal kesuburan. Mulai dari patung Dewi Sri, motif yang mengambil inspirasinya, lukisan sawah, dekorasi bulir padi, dan sebagainya hampir selalu dijumpai dalam kekaryaan di berbagai daerah pada masa yang berbeda. Masyarakat yang memiliki pengalaman hidup beragam dan bicara dalam ratusan bahasa namun sama-sama berbagi sinar matahari sepanjang tahun dengan tanah vulkanisnya yang begitu ramah pada berbagai benih bisa menjadi penjelasannya. Namun ini hanya satu sudut pandang, seorang seniman dengan kebebasan jiwanya dan keluasan pandangannya membuka peluang ekspresi yang tidak tentu batasnya, bahkan seringkali melampaui zamannya.
Permasalahan penulisan seni rupa Indonesia saat ini tidak semata berada dalam kegamangan memilih metode paling tepat namun mungkin diperlukan keterbukaan menerima sudut pandang yang plural untuk meninjau setiap sudut seni rupa Indonesia dengan pendekatan yang mungkin tidak serupa melalui berbagai eksperimen. Ada karya seni yang lebih tergali pemaknaannya melalui metode formalisme Fry, sebagaimana bisa jadi sangat banyak yang begitu menarik saat dikupas dengan pendekatan Riegl. Bahkan bisa jadi ditemukan cara pembacaan lain yang lebih bisa menggambarkan hubungan-hubungan antara karya, seniman, dan spirit zamannya. Aminudin Siregar menyebutkan pendekatan Indonesia-sentris ala Trisno Sumardjo pun cukup menarik, sayang belum ada yang serius menggarapnya.
Hal terpenting adalah kedisiplinan untuk seturut dengan metode yang dipilih dan kecermatan menghadapi fakta kekaryaan dan arsip yang terkait setiap upaya penulisan, untuk menghindarkannya berkelindan dengan berbagai mitos yang alih-alih memberi gambaran jelas malahan melukis kekaburan jejak Seni Rupa Indonesia. Dengan demikian penulisan sejarah seni rupa setidaknya bisa diharapkan terbebas dari fungsi sebagai alat politik atau kekuasaan manapun meskipun senyatanya karya itu sendiri takkan lepas dari ekspresi dan respon estetis sang seniman terhadap kekuasaan, ketidakadilan, perjuangan, kemajuan, serta penderitaan bangsanya atau sesama manusia pada umumnya.