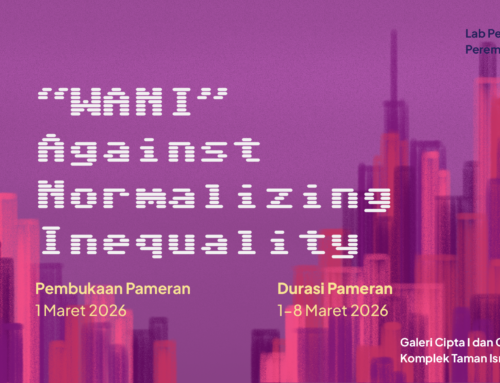Oleh: Rainda Satrya Janari
Tulisan ini lahir dari proses panjang penulis dalam membaca berbagai literatur mengenai sejarah secara umum dan sejarah dalam konteks seni secara khusus. Selain itu, penulis juga banyak terlibat dalam seminar, lokakarya penulisan, serta diskusi-diskusi bertema sejarah yang memperkaya sudut pandang dan pemahaman penulis terhadap bidang ini. Melalui rangkaian pengalaman tersebut, tulisan ini hadir sebagai sebuah opini reflektif yang merangkum berbagai pemikiran, pengamatan, dan kegelisahan yang penulis temui selama bergelut dengan praktik penulisan sejarah, terutama dalam ruang lingkup seni. Penulis berharap refleksi ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi percakapan yang lebih luas mengenai bagaimana sejarah seni dipahami, ditulis, dan dihayati.
Pengetahuan tentang sejarah seni kerap dibentuk melalui beberapa jalur yang tampak mapan: pameran arsip, buku naratif, dan biografi seniman. Di dalam ruang pamer arsip, pengunjung menjumpai foto-foto lama, katalog pameran, undangan yang sudah menguning, dan potongan teks yang dipilah-pilah sebagai penanda berbagai peristiwa. Sementara itu, buku sejarah seni dan biografi menyajikan rangkaian cerita yang tampak runtut: ada awal, ada puncak, ada tokoh-tokoh yang diberi penekanan, dan ada karya-karya yang ditempatkan sebagai penanda zaman. Dari semua bentuk ini, terbentuk kesan bahwa sejarah seni adalah sesuatu yang sudah disusun, disepakati, dan tinggal dibaca. Seolah-olah penulis sejarah seni hanya perlu menghimpun kembali apa yang sudah tersedia. Tulisan ini berangkat dari dugaan bahwa gambaran tersebut mungkin terlalu menyederhanakan kenyataan. Ada kemungkinan bahwa praktik penulisan sejarah seni selalu lebih rumit, karena melibatkan negosiasi antara apa yang tercatat dan apa yang hanya dapat dibayangkan.
Arsip seringkali dibayangkan sebagai pondasi yang kokoh. Dokumen-dokumen yang tersimpan—baik dalam bentuk fisik maupun digital—memberi rasa pasti: di sana tercantum tanggal, nama, tempat, dan judul. Pameran arsip memperlihatkan bahwa masa lalu meninggalkan jejak yang dapat dilihat, dibaca, dan dirujuk. Buku naratif dan biografi seniman kemudian menyusun jejak ini menjadi cerita yang lebih panjang. Di titik ini, arsip tampak menawarkan kenyamanan bagi penulis sejarah seni. Dengan mengacu pada arsip, penulis dapat merasa bekerja di atas bahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan arsip, sebaliknya, mudah dibayangkan sebagai situasi yang membuat penulisan menjadi rapuh dan rawan dianggap sebagai rekaan semata.
Namun, jika arsip dilihat sedikit lebih dekat, muncul kemungkinan bahwa ia tidak pernah benar-benar utuh. Arsip, dalam berbagai bentuknya, selalu merupakan hasil dari pilihan: pilihan apa yang disimpan dan apa yang dibiarkan berlalu; pilihan siapa yang dicatat dan siapa yang tidak; pilihan momen mana yang dianggap layak diabadikan dan mana yang dianggap biasa saja. Ada pameran yang didokumentasikan secara lengkap, tetapi ada juga pertemuan, diskusi, atau inisiatif seni yang mungkin tidak pernah sempat masuk ke dalam katalog atau dokumentasi visual. Ada seniman yang namanya muncul berulang kali di berbagai dokumen, sementara yang lain hanya diketahui lewat cerita atau bahkan sama sekali menghilang dari catatan formal. Dari sini, mungkin dapat dikatakan bahwa arsip tidak hanya menyimpan ingatan, tetapi juga menyimpan jejak seleksi dan penghapusan.
Selain itu, arsip biasanya menyimpan informasi yang bersifat formal dan singkat: tanggal pembukaan, nama ruang pamer, daftar karya, nama kurator, dan potongan teks pengantar. Sementara itu, dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilingi peristiwa seni sering kali hadir hanya secara implisit—jika pun ada. Kondisi ekonomi para pelaku seni, relasi kuasa antara institusi dan individu, perubahan sosial yang memengaruhi cara karya diterima, hingga atmosfer politik yang menekan atau justru mendorong produksi tertentu, tidak selalu tercermin langsung di dalam dokumen. Bisa dibayangkan bahwa di balik satu katalog pameran yang tampak sederhana, terdapat jaringan situasi yang jauh lebih kaya dan kompleks, yang tidak sepenuhnya hadir di arsip.
Dalam keadaan seperti itu, penulis sejarah seni tidak hanya berhadapan dengan “apa yang tertulis”, tetapi juga dengan “apa yang mungkin tidak tertulis”. Ketika melihat arsip, penulis tidak hanya dapat bertanya “apa yang terjadi?”, tetapi juga “apa yang mungkin terjadi di sekitar peristiwa ini?” dan “apa yang absen dari dokumen ini?”. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membuka jalur renungan bahwa penulisan sejarah seni tidak berhenti pada pengumpulan data, melainkan juga pada upaya memahami keterbatasan data tersebut. Arsip dapat dipahami sebagai salah satu titik berangkat, bukan sebagai garis akhir yang menutup semua kemungkinan.
Di luar arsip tertulis, dapat dibayangkan adanya wilayah yang lebih cair, tempat berbagai cerita, kesan, dan ingatan bergerak tanpa bentuk yang tetap. Misalnya, cerita yang beredar dari mulut ke mulut tentang pameran yang batal terjadi, tentang karya yang disensor, tentang konflik kecil yang memengaruhi siapa yang tampil dan siapa yang tidak, atau tentang ruang-ruang alternatif yang hanya bertahan sebentar lalu hilang tanpa jejak dokumenter yang jelas. Kadang-kadang, peristiwa-peristiwa ini hanya hidup dalam fragmen ingatan beberapa orang, diceritakan kembali dengan detail yang berubah-ubah, dan tidak pernah masuk ke dalam laporan resmi. Di sini, sejarah seni menghadirkan dirinya sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh arsip, tetapi juga tidak sepenuhnya dapat diabaikan.
Ketika penulis mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan semacam ini, imajinasi mulai tampak sebagai sesuatu yang ikut bekerja. Imajinasi, dalam konteks ini, bukan harus dipahami sebagai kebebasan untuk mengarang, melainkan sebagai upaya untuk membayangkan hubungan di antara fragmen yang tidak lengkap. Jika sebuah arsip hanya menunjukkan bahwa pada tanggal tertentu diadakan pameran dengan daftar karya tertentu, sementara cerita lisan menyinggung adanya ketegangan di balik penyelenggaraan pameran itu, penulis mungkin terdorong untuk membayangkan bahwa peristiwa seni tersebut tidak hanya terdiri dari apa yang tertulis di katalog. Penulis dapat membayangkan adanya diskusi-diskusi di luar ruang pamer, negosiasi yang tidak tercatat, atau perasaan-perasaan yang muncul tetapi tidak pernah masuk ke dalam dokumen.
Di sini, imajinasi bekerja sebagai cara untuk menyadari bahwa apa yang tertulis tidak pernah sepenuhnya mewakili apa yang terjadi. Namun, imajinasi juga tidak dapat dibiarkan sepenuhnya lepas dari kendali. Penulis perlu menjaga jarak agar tidak menjadikan kemungkinan-kemungkinan ini sebagai kebenaran yang pasti, tetapi tetap menghormatinya sebagai bagian dari cara memahami masa lalu. Dalam tulisan, hal ini mungkin bisa dilakukan dengan menandai pernyataan yang masih berupa dugaan, dengan menggunakan ungkapan seperti “kemungkinan”, “bisa jadi”, atau “tidak tertutup kemungkinan bahwa…”. Dengan demikian, pembaca diajak untuk melihat bahwa penulis sedang bergerak di wilayah interpretasi, bukan menyampaikan fakta baru yang tidak terbantahkan.
Jika kedua sisi ini diperhatikan—arsip yang selektif dan imajinasi yang bekerja di celah-celahnya—maka penulis sejarah seni tampak berada di antara dua kecenderungan ekstrem. Di satu ekstrem, terdapat kecenderungan untuk hanya mengakui apa yang terdokumentasi, sehingga sejarah seni dipersempit menjadi kumpulan data yang dapat diverifikasi. Pendekatan ini memberikan kesan mantap, tetapi berisiko mengabaikan berbagai dimensi pengalaman yang tidak pernah masuk catatan. Di ekstrem lain, terdapat kecenderungan untuk terlalu mengandalkan imajinasi dan cerita lisan tanpa mempertimbangkan batasan sumber, sehingga penulisan sejarah seni berisiko kehilangan pijakan dan sulit dibedakan dari fiksi. Keduanya sama-sama menyimpan risiko yang perlu disadari.
Daripada memilih salah satu secara mutlak, penulis mungkin dapat memikirkan posisi di antara keduanya. Di satu sisi, arsip tetap diperlukan sebagai acuan dan titik orientasi. Di sisi lain, kesadaran bahwa arsip tidak lengkap membuat penulis lebih peka terhadap apa yang absen, terhadap cerita-cerita yang hanya hadir sebagai rumor, dan terhadap konteks sosial yang mungkin tidak tercatat. Imaginasi kemudian dapat dipahami sebagai cara untuk menjaga agar absensi tersebut tetap terlihat, bukan sebagai upaya untuk mengisi semua kekosongan seolah-olah dapat diketahui secara penuh. Dengan demikian, penulis tetap menghormati batas-batas sumber, tetapi tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa masa lalu lebih luas daripada dokumen yang sampai ke tangan kita.
Sikap semacam ini juga memiliki implikasi terhadap cara penulis memposisikan diri sendiri di dalam teks. Alih-alih menghilangkan kehadiran penulis, teks dapat mengakui bahwa sudut pandang tertentu sedang digunakan. Misalnya, penulis dapat menandai bahwa penjelasan yang diberikan adalah salah satu kemungkinan bacaan atas arsip yang tersedia, bukan satu-satunya cara membacanya. Penulis juga dapat menunjukkan bahwa pilihan terhadap arsip tertentu, penekanan pada aspek sosial atau politik, dan perhatian pada cerita lisan merupakan bagian dari cara pandang tertentu yang dapat berbeda dengan penulis lain. Pengakuan semacam ini tidak serta-merta melemahkan tulisan, tetapi justru dapat menambah kejelasan tentang bagaimana teks tersebut dibangun.
Dalam konteks ini, penulisan sejarah seni dapat dipahami sebagai praktik yang bersifat sementara dan terbuka. Sementara, karena selalu mungkin bahwa di masa depan akan muncul arsip baru, kesaksian baru, atau cara baca baru yang mengubah pemahaman terhadap peristiwa yang sama. Terbuka, karena penulis menyadari bahwa apa yang ditulis bukanlah penutup pembicaraan, melainkan bagian dari percakapan yang lebih panjang tentang masa lalu. Kesadaran ini juga dapat mendorong penulis untuk bersikap lebih hati-hati dalam menyatakan sesuatu sebagai fakta yang final, dan lebih cenderung untuk membiarkan ruang bagi koreksi, tambahan, atau bahkan sanggahan.
Renungan tentang arsip dan imajinasi ini tidak berniat menawarkan rumusan metodologis yang baku, melainkan hanya menggarisbawahi beberapa kemungkinan sikap. Penulis sejarah seni mungkin dapat melihat arsip sebagai bahan yang penting tetapi tidak lengkap; melihat cerita lisan dan fenomena yang tidak terdokumentasikan sebagai penanda bahwa ada pengalaman yang belum sepenuhnya masuk ke dalam teks; serta melihat imajinasi sebagai bagian dari proses memahami, bukan sekadar sebagai kebalikan dari kebenaran. Dengan cara pandang seperti itu, sejarah seni dapat dipahami bukan hanya sebagai kumpulan catatan tentang apa yang terjadi, tetapi juga sebagai upaya terus-menerus untuk mendekati apa yang mungkin telah terjadi, dengan segala keterbatasan pengetahuan yang dimiliki.
Pada akhirnya, berada “antara arsip dan imajinasi” dapat dilihat sebagai posisi yang wajar bagi penulis sejarah seni. Di satu sisi, penulis tidak perlu menolak arsip atau meremehkannya. Di sisi lain, penulis juga tidak harus menyingkirkan imajinasi seolah-olah ia selalu berkonotasi negatif. Keduanya dapat dipertemukan dalam sikap yang waspada: waspada terhadap klaim kepastian yang terlalu cepat, dan waspada terhadap dorongan untuk mengisi semua kekosongan. Di antara dua kewaspadaan itulah penulisan sejarah seni dapat berlangsung—sebagai rangkaian upaya untuk memahami masa lalu dengan cara yang rendah hati, terbuka, dan sadar akan batas-batasnya sendiri.