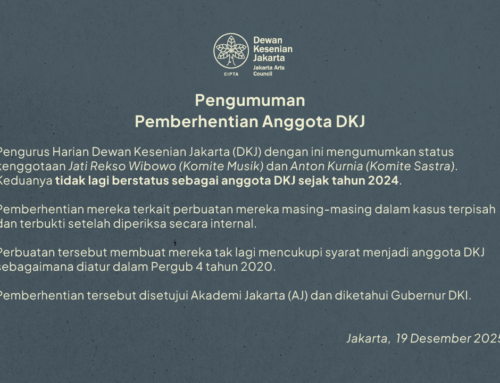Djakarta International Theater Platform atau DITP 2025 mengusung tema Bumantara dengan menelisik keberadaan “Rumah” sebagai ruang domestik serta ruang pertunjukan yang menciptakan kolaborasi serta koneksi bersama.
Simposium internasional yang berlangsung selama dua hari pada 7-8 Agustus 2025, mengusung pembahasan akan rumah pertunjukan yang membuka ruang kolaborasi, partisipasi, serta kolektivitas di Asia Tenggara. Perbincangan hangat yang terjadi di PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM) ini, mengangkat tema, “Unhousing the Region: What, Where and When is Southeast Asia?” serta “Unstable Stages: Who Performs, Who Listens, Who Decides?”
“Unhousing the region: What, Where and When is Southeast Asia?” sebagai simposium internasional yang diselenggarakan pada 7 Agustus 2025 sebagai salah satu rangkaian acara DITP 2025, mencoba mendefinisikan kembali makna “Rumah” sebagai suatu ruang yang terus berubah. Helly Minarti, seorang peneliti dan kurator seni yang menetap di Yogyakarta, memberi suatu metafora utopis akan “Rumah” melalui contoh lagu band Naif berjudul, Rumah yang Yahud. Realitas yang dihadapi sekarang mengemban suatu makna kebersamaan, layaknya pada lirik lagu Naif, “Semua milik bersama”, sebagai kontur dalam membentuk koneksi serta kolaborasi dalam ruang itu sendiri.
Kathleen Ditzig, seorang sejarawan dan kurator seni dari Singapura, menjelaskan makna dari seni yang hadir dari dan untuk sekitar kita. Bumantara baginya merupakan sebuah konsep yang menggambarkan Asia Tenggara, memberi ruang untuk menunjukkan karya seni yang kita miliki. Seni dimaknai sebagai ruang dan alat yang membangun solidaritas pada masyarakatnya, terkhusus Asia Tenggara.
“Exhibition produces the way we see the world,” menjadi salah satu yang ditegaskan oleh Kathleen dalam simposium ini.
Setelah melihat “Rumah” sebagai sebuah ruang terlebih dalam berkesenian untuk menunjukkan kolaborasi, June Tan, seorang produser, penulis naskah, dan anggota dari kolektif seni Five Arts Centre dari Malaysia, mencoba mendobrak dengan membayangkan kembali ide dari “Rumah,” yang secara ekologis terdapat aspek organik dan inorganik. Dalam “Rumah,” memungkinkan suatu shared experience terjadi, atau dalam keseharian kita mengenalnya sebagai gotong royong. Shared experience memungkinkan untuk melakukan story telling terhadap sejarah yang kita miliki, bukanlah mengubah sejarah, tetapi menarasikannya.
Simposium internasional pertama ditutup dengan pemaknaan kembali akan “Rumah” serta diskusi melalui tanya jawab yang memantik jawaban akan konsep budaya yang terus berkembang seiring berjalannya waktu.
Kedua
Pada 8 Agustus 2025, simposium internasional kedua bertajuk, “Unstable Stages: Who Performs, Who Listens, Who Decides?” dilaksanakan dengan sebuah pertanyaan pemantik, siapa yang berhak berkumpul dalam ruang tersebut? Bagaimana menciptakan ruang atau karya dari sesuatu yang asing bagi kita?
Joned Suryatmoko sebagai pelaku teater, aktor, dan penulis membagikan pengalaman akan rasa. Rasa yang membentuk suatu pengalaman akan pertunjukkan seni yang ditunjukkan. Afeksi menjadi sebuah kunci bagaimana pengalaman dari peraga kepada audiens membuka ruang untuk merasakan lebih dalam karya seni tersebut. Joned sempat menyinggung pertunjukkan dari Tapir Studio, Malaysia dengan karya “Tidur Sore” dalam membagikan pengalaman merasakan rasa dalam menonton.
Berangkat dari landasan tersebut, diskusi mengalir pada kehadiran ruang kolektif seni teater yang memulainya dengan keterasingan masyarakat terhadap komunitas maupun topik yang dipertunjukkan, bagaimana seni dapat membuka rasa kebersamaan tersebut.
Pathipon atau yang disapa Miss Oat, membagikan pengalaman komunitas Queer dalam menciptakan ruang berkesenian terkhusus teater di Thailand sebagaimana dirinya adalah seorang pelaku teater. Sejarah akan komunitas Queer yang berkembang di Thailand, menjadi suatu rasa yang membangkitkan ruang seni teater dalam sebuah festival bernama, Homo Haus. Miss Oat memberikan sebuah refleksi dalam melihat Queer People sebagaimana adalah Queer, untuk lebih memahami identitas mereka. Ruang membuka hadirnya komunitas yang menjadi ruang aman bagi mereka yang pernah terasingkan. Teater menjadi salah satu ruang yang berangkat dari pengalaman bersama, dan menjadi sebuah komunitas yang aman.
Selain melalui pengalaman komunitas Queer, bagaimana seorang seniman berkarya di tengah konflik negara menjadi pengalaman yang diceritakan oleh Kamizu, seorang seniman asal Myanmar yang karyanya dapat kita kunjungi di Galeri Cipta 2, Taman Ismail Marzuki, yang berjudul “Dwelling / Departing”.
Bagaimana seniman Myanmar berkarya di tengah konflik militer yang sedang terjadi, merupakan refleksi yang dihadirkan Kamizu pada simposium ini. Seni yang merupakan ruang, dijadikan sebuah propaganda yang menargetkan para seniman itu sendiri. Jika seorang seniman membawa topik yang sensitif, menyinggung konflik atau negara, mereka akan ditangkap atau hilang. Situasi ini membuat suatu perubahan dari para seniman termasuk Kamizu untuk terus berkarya dan bertahan–”working and surviving”. Pengalaman ini juga yang menjadi titik berangkat Kamizu dalam pamerannya yang mengajak audiens merefleksikan kembali “rumah” yang diinginkan.
Diskusi ditutup dengan pemaparan terakhir dari Wilson “Bong” Billones, seorang direktur program teater, PETA. PETA yang hadir pada tahun 1967, merupakan sebuah komunitas yang memberikan ruang bagi para pelaku teater untuk berkoneksi dan menciptakan karya bersama. Bermula dari “Kapwa” bahasa Filipina yang dapat diartikan sebagai helping, sharing, supporting, dan living, menjadi nilai yang berkembang pada masyarakatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, berangkat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Ferdinand Marcos, “Kapwa” luput dari masyarakat, bukannya berkoneksi malah terpisahkan. Proses menceritakan kembali atau menarasikan menjadi bentuk perayaan untuk keluar dan membangkitkan “Kapwa” kembali. PETA sebagai suatu komunitas teater lantas hadir dan berkembang untuk merayakan narasi masyarakat Filipina.
Tentang Simposium dan Bumantara
Simposium internasional yang terjadi selama dua hari ini, sampai pada suatu refleksi bahwa “Rumah” merupakan sarana, ruang, terciptanya praktik berkesenian yang berangkat dari keterasingan serta “rasa” bersama. Simposium ini membuka ruang diskusi dari para seniman sebagai bentuk penataan kembali “rumah” yang tidak semerta-merta sebagai wujud fisik saja, tetapi bentuk solidaritas, kolaborasi, bahkan perlawanan. Berangkat dari metafora utopis akan “rumah” hingga pengalaman yang dirasakan seniman, komunitas Queer, hingga dihantui penindasan militer, membuka ruang bagi seni untuk merefleksikan, melawan, serta membersamai.
“Bumantara” sebagaimana tema dari DITP 2025 ini, tak hanya membentang di antara langit dan bumi, namun melampauinya menciptakan titik temu dalam berkarya.
(Marcelina Elenora Terainconita Tukan)