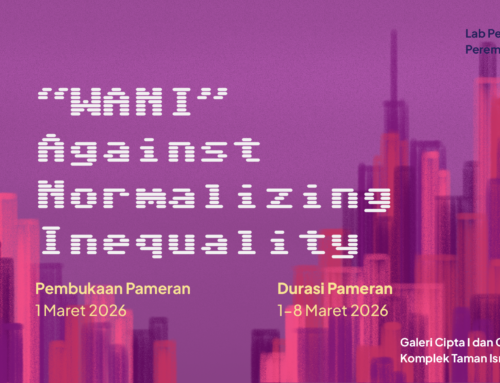Oleh: Widyanuari Eko Putra
“Kota adalah hasil karya manusia terbesar…”
(Farid Rakun)
Kota tidak lahir dari rahim Tuhan. Kota tidak pernah lahir untuk tiba-tiba menjadi bentuk yang “jadi”. Kota selalu terbentuk dari tahapan-tahapan yang kemudian yang membawanya pada bentuknya yang paling modern.
Kita tidak pernah yakin, bagaimana kota “mengada”, kemudian manusia merasa seperti awam dan asing pada kota yang ia tinggali. Saya pun meyakini, kota tidak tiba-tiba ada. Ada gejala yang terjadi yang mencakup manusia, konstruksi kota, jalan, gedung, hingga mobilitasnya.
Kota, bagi keyakinan masyarakat luas, adalah tempat yang kini menjadi pertemuan segala “jenis” manusia. Jakarta, misalnya. Sebagai Ibukota, serta sebagai tempat di mana roda kehidupan manusia berputar, dalam hal ini sebagai ekonomi, politik, dan pemerintahan, ia memiliki magnet tersendiri untuk menyedot perhatian masyarakat Indonesia.
Manusia datang dan berlalu di Jakarta. Adakah yang lebih akrab dari kedatangan dan kepergian di kota ini? Tidak. Saya merasa Jakarta adalah sebuah persimpangan besar. Kita bisa melihat orang-orang berpengharapan pada Jakarta, meski di sana seolah tidak pernah menjanjikan apa-apa.
Jakarta, khususnya, dan kota-kota besar lainnya, pada khususnya, adalah ruang yang hidup dalam imajinasi manusia Indonesia. Kita belum lupa lirik lagu Koes Plus yang masyhur itu: “Ke Jakarta aku ‘kan kembali, walaupun apa yang ‘kan terjadi…”. Pahitnya ibukota tak pernah memberi jera pada yang pernah mengisap “madunya”.
Kota selalu menciptakan kesan bahkan gesekan, kata Farid Rakun, dosen Arsitektur UI. Setiap pertemuan, untuk kali pertama atau pun yang ke sekian, tak pernah tidak, telah menyisakan sebuah kesan. Saya datang ke Jakarta, seingat saya, lima belas tahun silam. Maka membandingkan kota ini dengan apa yang pernah saya alami dulu, tentu saja kurang pantas. Bukankah lima belas tahun adalah waktu yang cukup untuk menggelar sebuah perubahan yang besar dan menyeluruh?
Maka, menyetujui perkataan Mas Farid, kedatangan saya di kota ini, juga teman-teman yang datang dari berbagai daerah di Indonesia: Semarang, Jogja, Makasar, Aceh, Padang Panjang, Lombok, kesan dari masing-masing kami tentu berbeda. Seperti teman-teman yang lain, yang berkisah tentang apa-apa saja yang mereka temui kali menginjak tanah Jakarta, saya pun mengalaminya.
Pada sesi perkotaan ini, Mas Farid mengajukan sebuah pertanyaan sedehana: adakah cerita dalam perjalanan dari penginapan menuju tempat lokakarya (13/12/2014) berlangsung. Pertanyaan sederhana, tapi tak sesederhana jawaban yang bakal muncul.
Adalah adegan membeli sebungkus rokok di sebuah warung kecil, di pinggir jalan tikus ketika menuju tempat lokakarya ruangrupa. Saya tak menyesal jadi pecandu rokok, tapi saya kecewa jika ada pedagang yang menjual sebungkus rokok dengan harga yang semena-mena. Semena-mena? Berlebihankah saya? Saya kira tuduhan tersebut cukup adil. Di mini market, meski saya kurang sreg membeli rokok di sana, harga sebungkus rokok kesukaan saya berkisar antara Rp.11.000-Rp.12.000. Maka saya perkirakan, harga di warung pinggiran tak jauh dari harga tersebut. Betapa saya seperti tiba-tiba tersengat arus listrik bertegangan tinggi, ketika mengetahui harga sebungkus rokok justru mencapai Rp.15.000/ bungkus. Saya terbakar gemas sendirian! Sehari di Jakarta, saya disuguhi sebuah kenyataan. Tapi, sudahlah. Biarlah kisah ini menjadi kenangan bagi saya. Haha.
Teman-teman saya punya berbagai kisah. Mada, perempuan sintal asal Bandung, mengisahkan pengalamannya saat melintasi gang sempit, di mana “tragedi” juga menimpa saya. Konon, di kaki perempuan enerjik ini, terbekaslah sebuah luka yang cukup besar akibat tersengat knalpot. Tentu kamu bisa membayangkan, sebuah luka menempel di betis gadis muda. Sungguh menyita perhatian siapa pun yang melihat, bukan?
“Kakinya ada tatonya ya, Neng?” seorang lelaki nyeletuk tanpa beban. Mada seperti mendapati dirinya terjun bebas dari jembatan Suramadu. Ada malu, sebel, bercampuraduk jadi satu. Bekas luka itu kini jadi sorotan lelaki yang gemar nongkrong di gang sempit itu. Begitulah pengalaman demi pengalaman tersaji. Setiap peserta lokakarya di ruangrupa mengisahkan apa yang dari masing-masing peserta temui.
Dari kejadian yang saya alami, bisa saya duga, begitulah sebuah kota menentukan sendiri harga sebungkus rokok secara “pantas”. Sebuah kota juga melahirkan masyarakat dengan segala macam keterbukaan. Fenomena sosial dan gejala perubahan ekonomi terjadi begitu pesat di sini. Saya barangkali menduga penjual rokok tersebut memanfaatkan tampang saya yang terkesan baru kali pertama datang ke Jakarta. Tapi, bisa saja saya salah dan harga rokok tersebut memang standar harga di warung tersebut. Atau, kejadian yang menimpa Mada, barangkali begitulah karakterisitik masyarakat di kampung-kampung Ibukota. Pada akhirnya, benar apa yang disampaikan Mas Farid, kota selalu menciptakan kesan, untuk tidak mengatakannya sebuah gesekan.