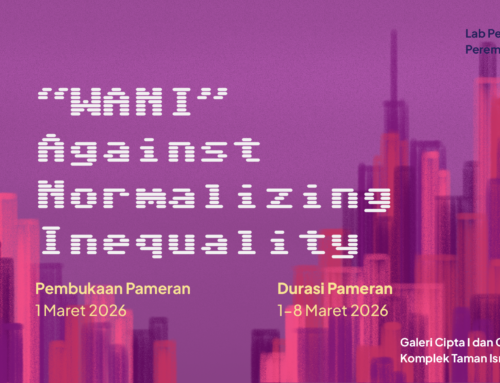Oleh: Diaz Ramadhansyah
Menggugat “Kitab Suci” di Ruang Lokakarya
Bagi hampir setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan seni rupa, buku tebal berjudul The Story of Art karya E.H. Gombrich sering kali diperlakukan layaknya “kitab suci”. Narasi yang dibangunnya begitu rapi, begitu meyakinkan, seolah-olah sejarah seni adalah sebuah garis lurus yang bergerak maju dari gua prasejarah Eropa menuju puncak kejayaan Renaisans dan berakhir di Modernisme Barat. Namun, duduk di dalam lokakarya “Pendekatan-pendekatan dalam Menulis Sejarah Seni” yang diampu oleh Aminudin TH Siregar, otoritas “kitab suci” itu perlahan-lahan terdekonstruksi.
Ada sebuah momen “gegar budaya intelektual” yang terjadi di ruangan itu. Sebuah kesadaran yang menohok bahwa sejarah seni, disiplin yang selama ini kita anggap objektif, ternyata tidak pernah netral. Ia bukan sekadar aktivitas administrasi untuk mencatat tahun, mengurutkan gaya, atau menghafal nama-nama seniman jenius. Lebih dari itu, historiografi seni adalah sebuah medan tempur ideologis. Ia adalah arena di mana ingatan kolektif dibentuk, dipilih, disortir, dan sering kali dipalsukan demi kepentingan sebuah narasi besar.
Selama bertahun-tahun, kita di Indonesia sering menelan mentah-mentah cara pandang Barat sebagai satu-satunya kebenaran universal. Kita mengukur kemajuan seni kita dengan penggaris mereka. Padahal, materi lokakarya ini menyingkap fakta telanjang bahwa fondasi disiplin ini, mulai dari tradisi biografi hingga formalisme yang dingin, dibangun di atas bias kultural Eropa yang sangat spesifik. Untuk benar-benar memahami seni Indonesia, kita tidak bisa sekadar meminjam kacamata itu. Kita perlu membongkar tumpukan mitos ini terlebih dahulu, memeriksa retakan-retakannya, sebelum akhirnya bisa menghargai betapa radikal dan pentingnya tawaran metodologis dari seorang wanita bernama Claire Holt.
Genealogi Bias dan Ziarah Elit Eropa
Sejarah seni yang kita pelajari tidak turun dari langit. Ia punya leluhur, dan leluhurnya adalah Eropa yang narsis. Jika kita menelusuri akarnya, kita akan tiba di Italia abad ke-16, tepatnya pada sosok Giorgio Vasari. Lewat bukunya yang monumental, The Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects, Vasari menanamkan sebuah mitos yang bertahan berabad-abad: bahwa sejarah seni adalah panggung drama bagi “individu jenius” (individual genius).
Dalam narasi Vasari, seni adalah kisah kepahlawanan individu seperti Michelangelo, Raphael, atau Leonardo da Vinci yang seolah memiliki sentuhan ilahi. Implikasinya bagi kita di Nusantara sangat fatal. Kita jadi latah memuja sosok individu dan melupakan tanah sosial tempat mereka tumbuh. Kita mencari “siapa pelukisnya”, padahal di banyak tradisi Nusantara, seni adalah kerja kolektif, sebuah doa bersama di mana ego individu lebur dalam tujuan komunal. Vasari membuat kita melihat seni sebagai barang steril yang terpisah dari denyut nadi masyarakat.
Obsesi ini bermutasi makin parah di tangan Johann Joachim Winckelmann pada abad ke-18. Saat itu, Eropa sedang dilanda demam Grand Tour, sebuah tradisi ziarah elit di mana para bangsawan muda Inggris dan Jerman berkeliling Eropa untuk “menyerap kebudayaan” dan mengoleksi barang antik. Di tengah euforia penggalian kota Pompeii dan Herculaneum yang terkubur abu vulkanik, Winckelmann merumuskan standar keindahan yang kelak menjadi penjara bagi seni non-Barat.
Ia menyebut standar itu dengan frasa Jerman yang terkenal: edle Einfalt und stille Grösse (kesederhanaan mulia dan keagungan yang tenang). Winckelmann memuja patung-patung Yunani yang putih, tenang, proporsional, dan minim ekspresi emosional. Baginya, itulah puncak peradaban. Implikasinya mengerikan: segala sesuatu yang tidak seperti Yunani, segala yang ekspresif, berwarna-warni, penuh ornamen, mistis, atau magis seperti seni kita di Nusantara, otomatis dianggap “belum matang”, “dekaden”, atau sekadar objek etnografi yang aneh. Standar Winckelmann menciptakan hierarki di mana Eropa berada di puncak piramida evolusi, sementara Asia dan Afrika berada di dasarnya.
Benteng Teori Modernisme
Tantangan bagi sejarawan seni Nusantara makin berat ketika memasuki abad ke-20. Di era ketika Claire Holt mulai meneliti, dunia sejarah seni dikuasai oleh raksasa-raksasa teori Barat yang membangun benteng intelektual yang kokoh.
Ada Aloïs Riegl, tokoh Mazhab Wina yang sebenarnya cukup progresif dengan konsep Kunstwollen (kehendak artistik). Riegl berusaha membuktikan bahwa perubahan gaya, misalnya transformasi motif daun acanthus dalam ornamen sejarah, bukanlah sekadar peniruan alam (mimikri) atau hasil keterbatasan teknik, melainkan dorongan internal dari jiwa zaman. Namun, meskipun Riegl memberikan otonomi pada seni, pemikirannya tetap terjebak dalam struktur evolusi gaya yang sangat Eropa-sentris.
Situasi menjadi lebih ekstrem dengan hadirnya Roger Fry dan Clive Bell yang membawa bendera Formalisme. Fry, yang terinspirasi oleh estetika Immanuel Kant tentang “kepuasan tanpa kepentingan” (disinterestedness), menegaskan bahwa seni harus dinilai murni dari bentuknya. Garis, warna, komposisi, dan harmoni tonal adalah raja. Sementara itu, “isi” karya, apakah itu cerita moral, fungsi ritual, atau konteks sosial, hanyalah polusi yang mengganggu kemurnian pengalaman estetis. Fry menggunakan lukisan Paul Cézanne sebagai model ideal: sebuah seni yang sibuk dengan persoalan visualnya sendiri dan terlepas dari beban narasi.
Di Amerika, pandangan ini diperkeras oleh kritikus Clement Greenberg yang mempromosikan teleologi modernis. Bagi Greenberg, sejarah seni adalah garis lurus menuju “abstraksi murni”. Seni yang maju adalah seni yang membuang beban representasi dan hanya bicara soal mediumnya sendiri (cat di atas kanvas).
Inilah benteng tinggi yang mengepung seni Indonesia. Jika kita memakai kacamata Fry atau Greenberg untuk melihat sebilah keris atau pertunjukan wayang kulit, kita akan kehilangan nyawanya. Seni Nusantara tidak pernah sekadar “bentuk yang enak dilihat” di retina mata. Ia tidak otonom. Ia adalah doa, ia adalah pedagogi, ia adalah perekat sosial, dan ia adalah jembatan menuju yang Ilahi. Membedah wayang dengan pisau formalisme yang dingin adalah sebuah malpraktik budaya. Kita akan mendapatkan data tentang bentuk wayang, tetapi kita akan membunuh rohnya.
Melirik Kiblat Lain
Lantas, apakah Barat adalah satu-satunya kiblat? Apakah kita dikutuk untuk selalu menjadi pengekor narasi Eropa? Ternyata tidak. Sejarah membuktikan bahwa narasi Eropa hanyalah satu dari sekian banyak kemungkinan cara memandang dunia.
Jauh di Tiongkok abad ke-9, seorang sarjana bernama Zhang Yanyuan menulis Lidai Minghua Ji (Catatan Pelukis Terkenal dari Segala Zaman). Parameter yang ia gunakan sama sekali berbeda dengan Vasari atau Winckelmann. Zhang tidak terobsesi pada evolusi gaya visual semata. Ia bicara soal moralitas. Bagi Zhang, seni lukis berfungsi untuk “melengkapi peradaban” dan “memperjelas hubungan manusia”. Ia menekankan pentingnya silsilah (lineage), transmisi ilmu dan kebajikan dari guru ke murid. Sejarah seni, di mata Zhang, adalah sejarah transmisi moral, bukan sekadar sejarah perubahan bentuk.
Contoh lain datang dari Turki modern lewat sosok Burhan Toprak. Dalam bukunya Sanat Tarihi (Sejarah Seni), Toprak menunjukkan bagaimana metodologi sejarah seni bisa dibajak dan diadaptasi untuk kepentingan pembangunan bangsa (nation building). Ia tidak menolak metode Barat, tetapi ia mengisinya dengan konten lokal. Ia menempatkan seni Islam dan Ottoman setara dengan Renaisans Italia, memberikan martabat baru bagi identitas Turki.
Pelajaran pentingnya sangat sederhana namun kuat: jika Tiongkok dan Turki berani memiliki logikanya sendiri, mengapa Indonesia harus tunduk, minder, dan terus-menerus menggunakan periodisasi Barat yang tidak pas dengan tubuh sejarah kita?
Claire Holt, Sang Penari di Antara Reruntuhan
Di celah kebuntuan itulah pemikiran Claire Holt hadir sebagai oase. Siapakah dia? Mengapa pandangannya begitu berbeda dari para peneliti kolonial Belanda sebelumnya?
Jawabannya terletak pada biografinya yang penuh warna dan “hibrida”. Holt bukanlah akademisi menara gading yang menghabiskan hidup di perpustakaan berdebu. Lahir di Riga, Latvia, pada tahun 1901, ia tumbuh di tengah guncangan Perang Dunia I yang memaksanya mengungsi ke Moskow. Pengalaman dislokasi ini memberinya perspektif sebagai “orang luar” yang abadi. Namun, formasi intelektual terpentingnya terjadi di New York, di mana ia belajar patung langsung dari maestro Kubisme Alexander Archipenko, sekaligus mendalami tari modern, jurnalisme, dan hukum.
Kombinasi latar belakang ini, sebagai pematung dan kritikus tari, adalah kunci emasnya. Ketika Holt datang ke Hindia Belanda pada tahun 1930-an dan melebur dalam budaya Jawa bersama arkeolog Willem Stutterheim, ia membawa seperangkat mata yang unik. Ia tidak melihat candi Borobudur atau Prambanan sebagai tumpukan batu mati yang statis. Ia melihatnya dengan “mata penari”: sebagai ritme yang membeku, sebagai gerak yang abadi, sebagai koreografi yang terpahat.
Lebih dari itu, Holt memiliki keberpihakan emosional. Berbeda dengan peneliti kolonial seperti J. de Loos-Haaxman yang hengkang atau bersikap sinis pasca-kemerdekaan, Holt justru kembali ke Indonesia pada tahun 1955 dengan perasaan sukacita. Ia ingin menyaksikan langsung bagaimana bekas jajahan Hindia Belanda bertransformasi menjadi bangsa baru bernama Indonesia. Simpatinya pada revolusi Indonesia membuatnya peka terhadap nuansa yang luput dari pandangan peneliti asing lainnya. Ia menyadari bahwa untuk memahami seni di tanah ini, seseorang tidak cukup hanya menjadi sejarawan seni. Ia harus menjadi “filsuf, sosiolog, antropolog, psikolog, dan seniman sekaligus”.
Melawan Arus Diskontinuitas
Kontribusi intelektual terbesar Holt adalah keberaniannya menantang debat paling panas di era 1950-an: debat tentang “Diskontinuitas”.
Pasca-kemerdekaan 1945, semangat nasionalisme di Indonesia sedang membara. Para kritikus dan seniman, seperti Trisno Sumardjo, S. Sudjojono, hingga Sanento Yuliman, dengan tegas menyatakan bahwa Seni Rupa Modern Indonesia “bukanlah lanjutan” dari seni tradisi. Bagi mereka, Revolusi Indonesia adalah sebuah Big Bang, sebuah ledakan awal yang menciptakan dunia baru. Masa lalu dianggap identik dengan feodalisme, keterbelakangan, dan masa-masa kelam penjajahan. Untuk menjadi modern, Indonesia harus memutus hubungan dengan masa lalunya. Sejarah seni dibayangkan seperti grafik “Gigi Gergaji”: penuh patahan dan pemutusan.
Namun, Holt menolak narasi “garis putus” yang traumatis itu. Dalam mahakaryanya Art in Indonesia: Continuities and Change (1967), ia mengajukan tesis Continuities (Kesinambungan). Bagi Holt, waktu di Nusantara tidak berjalan linier dan terputus-putus. Waktu adalah arus sungai yang terus mengalir, kadang tenang, kadang bergolak, tetapi airnya tetap sama.
Holt berargumen bahwa tradisi prasejarah tidak mati saat Hindu datang; ia hanya berakulturasi. Seni tradisi tidak lenyap saat Modernisme tiba; ia bertransformasi. “Jiwa” dari kebudayaan itu tetap bertahan meskipun “baju”-nya berganti-ganti mengikuti zaman. Modernitas, bagi Holt, bukanlah pembunuhan terhadap tradisi, melainkan metamorfosis tradisi itu sendiri.
Narasi Dewi Padi sebagai Bukti Empiris
Argumen tentang kontinuitas ini mungkin terdengar abstrak, tetapi Holt membuktikannya dengan sangat puitis melalui jejak visual tema kesuburan. Ia tidak menyajikan data ini sebagai daftar inventaris museum, melainkan sebagai sebuah perjalanan waktu yang menakjubkan.
Holt mengajak kita pertama-tama pergi ke Pulau Samosir di Sumatera Utara. Di sana, di atas tutup sarkofagus Batak Toba, terdapat figur batu seorang wanita. Gayanya kasar, primitive, kokoh, dan penuh tenaga purba. Ia memegang lesung, simbol abadi dari padi dan kehidupan. Ini adalah lapisan paling dasar dari memori kolektif kita.
Kemudian, Holt membawa kita melompat ke Jawa Tengah pada era klasik Hindu-Buddha. Kita dihadapkan pada patung perunggu Dewi Wasudhara (yang sering diidentikkan dengan Dewi Sri). Perhatikan transformasinya: gayanya kini menjadi halus, luwes, anggun, meminjam estetika ikonografi India. Namun, esensinya tetap sama: ia adalah ibu pemberi kehidupan, sang dewi padi.
Perjalanan berlanjut ke Bali di abad ke-20. Di sana, Holt menunjuk pada figur Cili yang terbuat dari daun lontar kering. Bentuknya sangat berbeda: geometris, pipih, dekoratif, dan sifatnya fana (akan layu dan dibuang setelah ritual usai). Namun, fungsi spiritualnya tetap untuk memuliakan padi.
Apakah perjalanan itu berhenti di masa lalu? Tidak. Inilah poin jenius Holt. Ia menunjukkan bahwa roh yang sama hadir kembali di kanvas pelukis modern berpendidikan Barat. Kita melihatnya dalam lukisan lanskap terasering sawah yang magis karya Kartono Yudhokusumo, atau dalam mural bertema “Pertanian” karya Srihadi Soedarsono.
Secara formal, keempat karya itu, batu Batak, perunggu Jawa, janur Bali, dan kanvas modern, berbeda total. Seorang formalis Barat seperti Roger Fry akan memisahkannya ke dalam ruangan museum yang berbeda dan bab buku yang tak berhubungan. Namun, dengan metode empati budayanya, Holt mampu melihat benang merah yang tak kasat mata: semuanya adalah manifestasi plastis dari dorongan purba yang sama, yaitu penghormatan pada daya hidup (life-force) dan kesuburan. Modernitas Indonesia tidak lahir dari ruang hampa; ia adalah percakapan panjang yang tak pernah putus dengan leluhurnya.
Menjadi Modern Tanpa Amnesia
Mempelajari historiografi melalui lensa Claire Holt pada akhirnya mengajarkan kita sebuah kerendahan hati intelektual. Sejarah seni bukan perlombaan lari menuju “kemajuan” visual ala Barat. Ia bukan tentang siapa yang paling realistis atau siapa yang paling abstrak. Sejarah seni adalah upaya merawat ingatan kolektif sebuah bangsa.
Pendekatan Holt menawarkan jalan keluar yang elegan dari jebakan Eurosentrisme dan kegamangan identitas pasca-kolonial. Ia mengajarkan bahwa kita bisa menjadi modern tanpa harus menjadi amnesia. Kita bisa maju ke depan tanpa harus membakar jembatan di belakang kita. Dengan melihat sejarah kita bukan sebagai garis lurus yang memisahkan “dulu” dan “sekarang”, melainkan sebagai siklus pembaruan yang terus-menerus, kita menemukan martabat kita kembali.
Seperti kalimat penutup yang ditulis Holt dalam bukunya, sebuah pesan yang masih relevan hingga hari ini: “Selagi negara Indonesia menjunjung tinggi persatuan, seni Indonesia akan selalu kaya akan keberagamannya.” Tugas kita, para penulis sejarah seni masa kini, adalah meneruskan metode empati tersebut. Kita harus berani menggali teori dari tanah kita sendiri, merumuskan cara pandang kita sendiri, dan berhenti sekadar menjadi konsumen pasif dari teori-teori impor yang tidak pernah dirancang untuk membaca tubuh budaya kita.