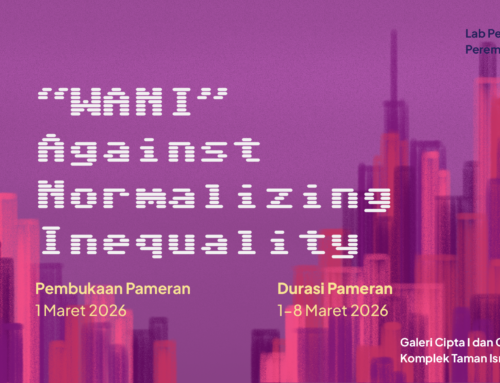oleh Wilujeng Anggraeni
Arjuna berumur 3 tahun,
dilahirkan sebagai anak terakhir,
dari ayah yang memiliki dua kakak.
Ardhan berusia 5 tahun,
dilahirkan sebagai anak pertama,
dari cucu sulung Bibi Arjuna.
Ardhan memanggil Arjuna dengan sebutan ‘kakek’.
Sebagai masyarakat Jawa, terdapat sebuah kebiasaan yang selalu diulang pada setiap kesempatan berkunjung ke rumah sanak saudara atau reuni keluarga. Kebiasaan yang dimaksud adalah mengurai silsilah keluarga dari buyut satu ke buyut lainnya dan menanamkan kepada generasi muda di keluarga masing-masing untuk mengingatnya. Kidungnya sama, setiap pengulangan nyaris tidak ada satu namapun yang diingat. Bagi generasi muda, sebuah keberuntungan jika pertanyaan yang muncul hanya sebatas siapa nama sanak saudara tertentu, tapi sungguh menjadi sial jika pertanyaan yang diperoleh adalah terkait dimana alamat atau cerita silsilahnya. Wah mampus sudah, Seketika saja jurus klasik untuk penanganan segala situasi dikeluarkan. Ya… tersenyum dengan polosnya sambil mengucapkan: “hehe, saya lupa”.
Salah satu tujuan dari kebiasaan ini adalah untuk mengetahui siapa yang lebih tua, dan siapa yang lebih muda bukan berdasarkan umur, melainkan dari silsilah buyut bahkan moyang sebelumnya. Pakem standar tua-muda ini berdasarkan dari moyang siapa yang lahir terlebih dahulu. Keluarga dengan silsilah moyang yang lahir duluan dianggap sebagai keluarga yang lebih tua. Praktek realisasinya adalah menentukan norma sosial berupa ‘yang muda’ sepatutnya berkunjung ke rumah ‘yang tua’ sebagai bentuk ngajeni marang wong tuwa. Praktek lainnya adalah penentuan kedudukan panggilan. Sebagai contoh yaitu panggilan ‘kakek’ untuk anak usia lima tahun kepada saudaranya yang berumur tiga tahun seperti studi kasus pada paragraf pembuka di awal tulisan ini.
Keunikan sistem ini membuat kita mawas terhadap siapa saja sanak saudara kita, tidak mengenal apakah dia muda atau tua, karena secara garis keturunan adalah lebih ‘tua’. Kemudian dianggap celaka jika ada orang tua yang apatis, tidak mau memberikan kidung silsilah keluarga kepada anaknya. Si anak akan lupa dan akhirnya tidak mengenal sanak saudaranya. Lebih celaka lagi jika sang anak yang apatis. Merasa bahwa silsilah sanak saudaranya bukanlah sebuah hal yang penting, tak lebih penting dari menghafal nama-nama personil boyband seventeen atau personil JKT-48.
Sebuah Proyek Performance Art “Sensus Dulur” mencoba untuk menjadi secuil solusi dari penyakit ‘apatis’ masa kini. Sensus Dulur mengadopsi dari Sensus Penduduk yang biasa dilaksanakan di masyarakat. Perbedaannya hanya pada segmentasi target orang yang akan disensus, yaitu sanak saudara dari keluarga terpilih. Performer akan beratribut lengkap selayaknya petugas sensus dan akan datang melakukan pendataan silsilah keluarga dari rumah ke rumah. Data yang dikumpulkan berupa alamat, foto rumah, wajah atau sketsa wajah, panggilan yang harus diterapkan sesuai silsilah kadang katut atau saudara yang masih terkait, dan wawancara dengan para buyut yang didokumentasikan dalam bentuk video. Hasil dari proyek ini berupa pameran hasil napak tilas suatu silsilah keluarga yang telah dipilih.
Dokumen hasil pendataan silsilah keluarga dari performer akan diakumulasikan dan dijadikan sebagai sebuah karya dalam bentuk instalasi, fotografi dokumentasi dan video documenter, pada pameran bertajuk “Kadang Katut”. Pengunjung dari pameran ini akan terbagi menjadi dua undangan yaitu undangan umum dan undangan khusus. Undangan umum ditujukan tidak terbatas pada siapapun sedangkan untuk undangan khusus adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Proyek Performance Art “Sensus Dulur”. Adapun pihak yang dimaksudkan adalah seluruh nama yang telah terlibat dalam proyek ini, para anggota keluarga dan sanak saudara dari keluarga terpilih. Pihak-pihak dengan undangan khusus ini akan menerima masing-masing buah tangan berupa CD berisi informasi silsilah keluarganya.
Akhir kata, pengantar ini diakhiri dengan sebuah harapan untuk dampak proyek seni ini. Meski proyek ini terkesan remeh dan tidak berdampak besar pada masyarakat secara luas, namun setidaknya proyek ini diharapkan bisa menjadi sebuah solusi dari secuil penyakit ‘apatis’ masa kini. Diharapkan pengunjung khusus dari generasi muda, tidak akan kesulitan untuk menjawab kuis dadakan pada sebuah reuni keluarganya. Memang skala dampak dari proyek ini tidak sehebat Jatiwangi Art Factory, tetapi mari kita percaya bahwa sekecil apapun dampak untuk diri sendiri dan orang terdekat kita merupakan dampak yang penting juga. Bukankah begitu?

Wilujeng Anggraeni tumbuh dan berkembang sebagai ‘anak seni’ di Samin (Sanggar Minat). Pengetahuan dan pengalaman seni banyak ia peroleh dari Samin. Sebagian besar tulisannya mengulas laporan acara seni seperti pameran seni rupa atau artikel acara insidental Sanggar Minat. Ia menulis pengantar pameran atau proyek art performance di Malang, dan pernah tergabung dalam tim kuratorial pameran HMJ Seni dan Desain “Alpa #5”.