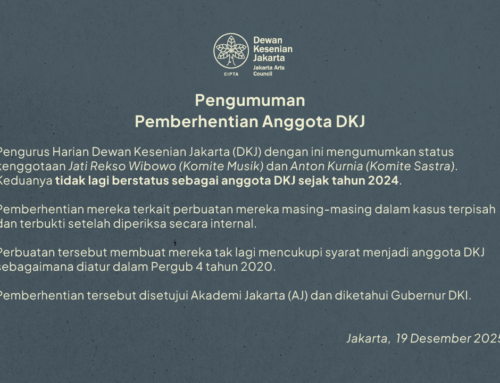Pertemuan dan kolaborasi musik diperlukan dalam membangun kesadaran bermusik serta mendukung kehadiran para komponis di Indonesia. Dewan Kesenian Jakarta melalui Komite Musik menyelenggarakan Pekan Komponis Indonesia 2025 sebagai ruang menjaga dan mengembangkan ekosistem musik kontemporer. Pekan Komponis Indonesia 2025 berlangsung selama lima hari pada 17-21 September yang bertempat di Graha Bhakti Budaya dan Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki.
Pekan Komponis Indonesia 2025 bertajuk “Activating the Ecosystem”, Komite Musik DKJ menggelar beberapa mata acara. The Literaly Muse merupakan gelaran yang mengundang enam komponis Indonesia diantaranya, Sri Hanuraga (Jakarta), Doni Dartafian (Bogor), Vima Fernandez (Ende), Jimmi Wijaya (Pekanbaru), Lucy Freia (Bandung), yang menunjukkan eksplorasi musik kontemporer melalui karya-karya mereka. Mata acara berikutnya adalah Senior Recital Series dengan mengundang komponis Dody Satya Ekagustdiman yang menggabungkan musik tradisional dengan kontemporer pada pertunjukannya di Graha Bhakti Budaya. Musical Games for Kids juga menjadi salah satu mata acara yang mengundang anak-anak Gantari Gita Khatulistiwa dengan sebuah lecture performance bersama Abdul Aziz dengan Ketua Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta, Arham Aryadi.
Pada 18, 19, dan 21 September dilaksanakan Diskusi Musik di Teater Wahyu Sihombing bersama Septian Dwi Cahyo, seorang komponis lulusan Graz University. Septian Dwi Cahyo melengkapi Pekan Komponis Indonesia 2025 dengan memberikan perspektif akan penciptaan instrumen baru di era kontemporer. Dirinya merefleksikan usaha para komponis melakukan upaya eksplorasi serta kolaborasi bermusik.
Materi pertama yang disuguhkan oleh Septian Dwi Cahyo pada hari kedua Pekan Komponis Indonesia 2025, menjelajahi eksplorasi alat musik baru dari para seniman bunyi Indonesia yang dijadikan media kritik sosial. Diskusi tersebut menelisik peran dari alat musik baru yang dikembangkan melalui penggabungan alat atau metode tradisional dengan kontemporer.
“Beberapa seniman bunyi menciptakan instrumen musik baru untuk memperluas tradisi, menghadirkan konteks baru, dan membangun dunia bunyi yang mereka inginkan,” tutur Septian dalam pemaparannya.
Terdapat enam objek yang dianalisis oleh Septian, salah satunya, Garu. Garu merupakan alat pertanian yang berbentuk seperti garpu. Pangan yang menjadi sektor kebutuhan masyarakat membuat penampilan Garu diatas panggung dalam instrument building, muncul sebagai suatu kritik sosial akan ketahanan pangan di Indonesia yang berlimpah namun tetap melakukan impor dari luar.
Pada 19 September dilakukan Diskusi Musik kedua oleh Septian dengan menelusuri teknik dalam bermusik–eksplorasi mikrointernal dan mikrotonal. Mikrointernal dan mikrotonal merupakan motif dalam musik yang menggunakan variasi sistem nada antara interval dan semiton. Septian menunjukkan beberapa karya dari para komponis Harry Partch seorang komposer dari Amerika serta Gérard Grisey dari Perancis yang melakukan eksplorasi dalam musiknya.
Eksplorasi mikro internal dan mikrotonal membuat para komponis berkreasi dengan notasi untuk menciptakan beragam motif. Eksplorasi ini biasanya menggunakan alat musik seperti piano dan biola. Motif yang dihasilkan membentuk suatu instrumen baru bahkan menggabungkan dua aliran yang berbeda. Salah satunya dilakukan oleh Steve Lehman dalam menggabungkan musik spektral–komposisi yang menggunakan representasi sonografi dan analisis matematis dengan musik jazz.
Setelah menjejaki musik dan instrumennya, pada hari terakhir penutupan Pekan Komponis Indonesia 2025, Septian mengisi diskusi dengan tema, “Text im Klang”, atau “Kata dalam Bunyi” yang diterjemahkan langsung dari bahasa Jerman. Musik memang adalah instrumen, namun teks juga hadir sebagai sumber inspirasi dalam musik. Diskusi ini memperlihatkan koneksi antara kata dan bunyi.
Teks yang biasanya hadir dalam cerpen maupun novel, ternyata dapat hadir juga dalam musik, sekalipun bukanlah yang utama. Teks dapat masuk ke dalam musik melalui interpretasi, tak perlu dengan kata-kata, tetapi juga dapat berbentuk sandi atau morse. Septian mendapat inspirasi dari puisi Orsolya Karafiáth dalam salah satu karya solo gitarnya. Inspirasi dari teks menuju musik muncul dari kesan yang dibaca, kemudian memunculkan ritme dan tensi dalam menciptakan instrumen.
Septian Dwi Cahyo juga terpikat dengan oleh Film Mother Dao, the Turtlelike (1995), dengan adegan seorang deklamator yang menempatkan musisi sebagai pencerita.
“Saya terpikat oleh penyampaian deklamator yang membacakan puisi ini di salah satu adegan di dalam film tersebut. Suaranya memberikan suasana yang mendalam puisi tersebut,” refleksi Septian terhadap peran musisi sebagai narator sembari menghasilkan bunyi di Pekan Komponis Indonesia 2025.
Diskusi Musik oleh Septian Dwi Cahyo ini melengkapi pertunjukkan karya-karya para komponis senior dan muda di Pekan Komponis Indonesia 2025 dengan menunjukkan proses kreasi serta eksplorasi mereka dengan alat musik. Musik tak hanya hadir sebagai produk kreatif melainkan juga sebagai kritik sosial, pengembangan serta perpaduan budaya. Pekan Komponis Indonesia 2025 menunjukkan para seniman bunyi yang melakukan eksperimen sembari merespon kondisi sosial serta membuka ruang pengembangan musik kontemporer.