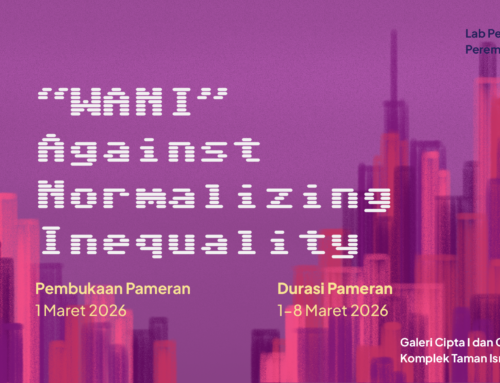Dimuseumkan. Itulah nasib yang kita anggap pasti bagi berbagai kenangan dan artefak masa lalu. Ia dibiarkan teronggok di pojok bangunan yang pengap, dan perlahan mulai tertutup debu dan jaring laba-laba. Pun, ia disajikan sebagai sepotong relik yang kering dan terasing dari situasi yang kita hadapi hari ini. Antara menjadikannya fosil atau memberi bumbu romantisme yang tidak perlu, kita bisa bicara panjang lebar soal nasib sejarah di Indonesia.
Pada hari kelima lokakarya kuratorial dan kritik seni rupa Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), kami mengkonfrontir persoalan ini. Bertempat di Gedung Jasindo, kompleks Kota Tua, Jakarta, kami menghadiri Kisah Konservasi, sebuah pameran yang diselenggarakan oleh UNESCO bekerjasama dengan Ruru Corps. Ketiga kurator di balik acara ini – Ardi Yunanto, Farid Rakun, dan Robin Hartanto – menyajikan kisah-kisah di balik lima cagar budaya bersejarah yang dikonservasi di Indonesia, dan mendapat penghargaan The UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation. Kelima cagar budaya tersebut adalah: Rumah Charles Prosper Wolff Schoemaker di Bandung (mendapat penghargaan pada tahun 2000), Gedung Arsip Nasional di Jakarta (2001), Jembatan Kebajikan di Medan (2003), Mbaru Niang di Desa Wae Rebo, Pulau Flores (2012), dan De Driekleur di Bandung (2014).
Ketiga kurator paham betul resiko menyajikan karya-karya arsitektur dan konservasi dalam konteks pameran; mereka bisa terjebak dalam detil-detil teknis yang kering. Maka, mereka pun menghabiskan waktu untuk meriset kelima lokasi tersebut secara mendalam melalui wawancara dengan berbagai sejarawan dan riset teks, dengan menaruh perhatian khusus pada narasi-narasi personal dan kisah sejarah. Temuan ini mereka sajikan dalam bentuk teks, foto, dan dokumentasi video yang ditata di lantai dua Gedung Jasindo.
Melangkah masuk area pameran, saya disambut oleh kisah konservasi Jembatan Kebajikan di Medan. Jembatan yang terbentang di atas Sungai Babura itu dibangun pada tahun 1916 untuk mengenang Tjong Yong Hian. Pengusaha sukses keturunan Tionghoa itu tersohor di seantero Medan karena kemurahan hatinya. Bersama Tjong A Fie, adiknya, ia mendanai pembangunan berbagai rumah sakit, tempat ibadah, panti jompo, dan sekolah. Namun, pada 2001, kondisi jembatan itu semakin mengkhawatirkan. Ornamennya yang biasa berkemilau di malam hari – mengundang julukan “Jembatan Berlian – sudah kusam, dan keterangan mengenai sejarah pendirian jembatan tak lagi dapat dibaca. Badan Warisan Sumatra (BWS), sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada konservasi berbagai cagar budaya, lantas berinisiatif mengkonservasi jembatan tersebut. Sebuah pesta terbuka diadakan di jembatan tersebut usai pembukaan kembali di April 2001. Keluarga Tjong Yong Hian pun mulai menggali kembali sejarah keluarga mereka dan mendirikan Museum Tjong Yong Hian pada 2011.
Berpaling dari Jembatan Kebajikan, saya bertemu dengan kisah Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia yang berliku-liku. Bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada, Jakarta, ini didirikan pada 1760 oleh Reinier de Klerk, pejabat VOC yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal VOC pada 1777. Sejarah bangunan ini tak lepas dari elitisme dan pergulatan panjang kolonialisme. Area antara Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk – lokasi rumah ini – dulu bernama Molenvliet, dan dikenal sebagai daerah peristirahatan dan pemukiman bagi para kalangan elit Eropa serta pejabat kolonial Hindia Belanda. Usai VOC pailit dan pusat kota Batavia dipindah dari daerah Kota ke Weltevreden (kawasan Medan Merdeka – Lapangan Banteng), Molenvliet semakin ramai dan perlahan kehilangan statusnya sebagai ‘pinggiran elit’. Rumah itu berpindah dari satu pemilik ke pemilik lainnya, dan berkali-kali berganti fungsi – menjadi panti asuhan dan kantor pertambangan sebelum jadi pusat arsip kolonial pada 1925. Pasca kemerdekaan Indonesia, bangunan ini ditempati oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Namun, gedung ini dikenal rawan banjir karena lokasinya yang lebih rendah dari permukaan laut. Pada 1976, ANRI pindah ke kawasan Ampera dan gedung ini perlahan melapuk. Baru pada 1997, konservasi besar-besaran dilakukan dan Yayasan Gedung Arsip Nasional didirikan pada 1998 untuk mengelola penggunaan bangunan tersebut.
Di ruangan sebelah, saya bertemu dengan kisah De Driekleur, sebuah bangunan tiga lantai di Bandung. Pada 1938, De Driekleur dibangun untuk menjadi rumah pribadi pengusaha Na Kim Hiok, namun pemerintah kolonial Belanda memaksanya menyerahkan rumah tersebut. Bangunan itu lantas digunakan sebagai rumah pejabat Belanda, dan kemudian dijadikan kantor berita Domei oleh pemerintah kolonial Jepang dan bahkan kantor Brimob di era setelah kemerdekaan. Bangunan cantik yang mencerminkan gaya Art Deco dan Art Moderne khas 1930’an ini kemudian terbengkalai, sebelum dibeli Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) pada 2006. Usaha konservasi pertama dilakukan pada 2007 dan mendapat penghargaan, namun arsitek Budi Lim berpendapat lain. Hasil konservasi 2007 dianggapnya berlebihan, dan malah menutupi serta mematikan berbagai karakteristik khas bangunan itu. Ia pun dipercaya BTPN untuk mengkonservasi ulang De Driekleur, yang dibuka kembali pada 2013.
Kisah tentang rumah Charles Prosper Wolff Schoemaker di Bandung ditampilkan di sebelah De Driekleur. Schoemaker, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang dikenal eksentrik, tersohor bukan saja karena karya-karyanya yang ikonik, namun juga karena hubungannya yang erat bersama salah seorang mahasiswanya di Technische Hoogeschool te Bandoeng (TH), Soekarno. Interaksi antara Schoemaker dan Soekarno dieksplorasi dengan baik di exhibit ini. Schoemaker kagum pada kecerdasan dan talenta Soekarno dalam bidang arsitektur, sementara Soekarno hormat pada sikap Schoemaker yang tak membeda-bedakan orang karena ras, dan mau berdialog dengannya sebagai kawan yang setara. Sayang, masa kolonialisme Jepang dan Perang Kemerdekaan mengguncang Schoemaker. Ia meninggal dalam keadaan bangkrut pada 1949, dan rumahnya yang penuh ornamen indah gaya Art Deco terbengkalai. Pada 1998, rumah itu nyaris akan dibongkar saat arsitek Dibyo Hartono mengunjunginya. Terganggu dengan penghancuran sebuah situs bersejarah, ia menulis artikel opini di koran yang menggerakkan pemilik rumah itu, Pramana Surjaudaja. Mereka pun sepakat untuk mengkonservasi rumah tersebut dan membukanya kembali pada 1999.
Terakhir, saya menikmati kisah konservasi Mbaru Niang, rumah tradisional Manggarai yang nyaris punah, namun masih bisa ditemukan di desa Wae Rebo, Manggarai, Pulau Flores. Serombongan arsitek nekad mendarat di Flores pada 2008 hanya berbekal foto dan pertanyaan tentang lokasi kampung adat Wae Rebo. Bagai berkelana ke antah-berantah, mereka akhirnya menemukan Wae Rebo dan bekerjasama dengan warga lokal untuk mengkonservasi rumah Mbaru Niang yang tersisa dan merekonstruksi ulang rumah-rumah baru. Mereka pun mengajak mahasiswa arsitektur dari berbagai universitas untuk turut serta dalam proses konservasi. Konsultan dan spesialis grafis dan perhumasan dipanggil untuk membantu rebranding desa Wae Rebo sebagai desa wisata. Kini, desa tersebut didatangi ribuan turis setiap tahunnya dan didapuk sebagai salah satu harta karun tersembunyi Indonesia.
Menariknya, Wae Rebo dijadikan preseden oleh ketiga kurator pameran ini untuk menunjukkan bagaimana konservasi dapat berdampak begitu jauh terhadap lingkungan sekitar. Sebelum konservasi Mbaru Niang dimulai pada 2009, jumlah pengunjung desa tersebut rata-rata hanya 45 orang per tahun. Angka tersebut perlahan naik jadi ratusan wisatawan per tahun, sebelum memuncak jadi 2.179 orang per Oktober 2014. Angka ini jauh di atas jumlah total penduduk Wae Rebo (320 jiwa) dan desa kembaran yang tak jauh dari sana, Kombo (1.200 jiwa). Melonjaknya jumlah wisatawan jadi pisau bermata dua bagi Wae Rebo. Di satu sisi, jelas ada keuntungan ekonomi yang dapat dinikmati oleh warga lokal. Di sisi lain, Wae Rebo mulai berubah. Desa itu mulai bertransisi jadi desa wisata purna waktu. Pekerjaan yang terkait industri pariwisata seperti pemandu, juru masak, dan juru angkut mulai dijadikan pekerjaan tetap oleh warga lokal. Para kurator pun menyampaikan kekhawatirannya bahwa influx wisatawan itu akan menguji ketahanan sumber daya di Wae Rebo, yang sejauh ini berkecukupan dengan mengandalkan sumber daya alam di sekitar saja. Dengan masuknya ribuan turis ke desa yang biasanya sepi, bagaimana cara mereka mengolah limbah cair maupun padat yang tentu akan dihasilkan dalam volume yang jauh lebih besar dari biasanya?
Bagi saya, ini kritik yang masuk akal. Pameran ini jelas tak ingin memberhalakan konservasi begitu saja – memuja dampak baiknya selagi menyembunyikan dampak-dampak buruk yang mungkin ia hasilkan. Konservasi juga menghasilkan berbagai pertanyaan yang wajib digali jawabannya. Tentang bagaimana pengelolaan situs itu, bagaimana dampaknya – baik dan buruk – pada lingkungan sekitar, dan tentang bagaimana konservasi mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran warga tentang sejarah situs tersebut. Dalam kasus Wae Rebo, eksposur media yang lebih luas menjadikan desa tersebut surga pariwisata baru, sehingga perhatian lebih pun diberikan oleh pemerintah. Alasannya sederhana: mereka punya aset baru yang perlu dilindungi.
Contoh kasus lain memberi indikasi berbeda. Gedung Arsip Nasional, misalnya. Berkali-kali banjir dan ruang yang tak lagi cukup untuk menampung arsip membuatnya dikosongkan, bahkan bisa dibilang ‘ditinggal’ oleh ANRI. Beruntung, ada inisiatif privat dari Yayasan Gedung Arsip Nasional yang menyelamatkan bangunan tersebut. Mereka memutar otak guna menggalang dana yang cukup untuk mengelola Gedung Arsip dengan baik. Lantas, eks rumah Gubernur Jenderal tersebut digunakan sebagai ruang pameran, makan malam kenegaraan, dan sering dijadikan venue pesta pernikahan. Setiap tahunnya, uang disisihkan untuk biaya perawatan bangunan tua tersebut. Co-kurator Robin Hartanto mengisahkan sebuah anekdot di mana ketua Yayasan Gedung Arsip Nasional pergi ke pacuan kuda di Sentul, dan mengumpulkan kotoran kuda untuk dijadikan pupuk bagi taman Gedung Arsip Nasional. Memang benar bahwa anekdot tersebut bisa jadi hanyalah anekdot. Namun, bagi saya kisah tersebut menggarisbawahi kegigihan dan kepedulian yang ditunjukkan para staff Yayasan Gedung Arsip Nasional untuk merawat bangunan itu.
Namun, menurut co-kurator Ardi Yunanto, sekitar 2009 lalu, sebuah polemik dimulai antara Yayasan dengan ANRI. Undang-Undang baru merevisi perpajakan, sehingga Yayasan diwajibkan membayar pajak yang lebih banyak dari sebelumnya. Ini jelas dianggap sangat memberatkan oleh Yayasan yang sejak awal sudah jungkir balik menyiasati keterbatasan dana. Sengketa ini berlanjut hingga akhir 2013 lalu, saat ANRI akhirnya mengambil alih pengelolaan Gedung Arsip Nasional, dan Yayasan Gedung Arsip Nasional segera menjadi non-aktif. Patut diakui, satu tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk menghakimi ANRI dan pengelolaannya atas Gedung Arsip Nasional. Rencana tentatif untuk membukanya bagi lebih banyak pameran, acara kebudayaan, dan meneruskan fungsi komersilnya sebagai venue pesta pernikahan didengungkan oleh ANRI. “Gue bukannya sok pesimis atau skeptis,” ujar Ardi. “Tapi, gue secara pribadi ragu bahwa ANRI bisa menunjukkan dedikasi yang sama dengan Yayasan dulu.”
Didirikannya Yayasan Gedung Arsip Nasional, menurutnya, adalah eksperimen yang menarik dalam pengelolaan cagar budaya yang independen dan tak banyak mendapat campur tangan pemerintah. “Itu bisa dilihat dari satu kasus ke kasus lainnya,” terang Ardi. “Misalnya, De Driekleur di Bandung justru bisa dirawat dan dikelola dengan sangat baik oleh elemen bisnis.” Entah takdir atau keberuntungan semata, penempatan waktu dari kedatangan Budi Lim ke De Driekleur sangat pas. Kala itu, BTPN kebetulan memang hendak mengubah strategi bisnis mereka, dan arsitektur indah De Driekleur dinilai bisa jadi salah satu bahan ‘jualan’ yang bisa menarik nasabah baru. Imbasnya, gedung bersejarah itu dirawat, namun belum sepenuhnya terbuka untuk publik. “Menurut BTPN, gedung itu terbuka buat publik.” Jelas Ardi. “Tapi, kebanyakan acara yang diadakan di situ masih acara untuk calon nasabah. Makanya kami tunjukkan di pameran ini kalau sebenarnya space itu bisa dipakai, supaya orang sadar.” Nasib serupa dialami rumah Schoemaker. Bangunan itu kini digunakan sebagai kantor bagi sebuah bank swasta. “Di depan, rumah Schoemaker jadi bank,” ungkap co-kurator Robin Hartanto. “Dan di belakang, ada yang ngebuka kafe. Tempat jualan. Itu gak kelihatan di foto.”
“Gue pribadi gak mau romantis soal fungsi bangunan itu sendiri sekarang,” lanjut Robin. “Tapi yang penting buat gue, ada dokumentasi yang baik soal sejarah bangunan tersebut, agar orang yang datang tahu.” Pendapat ini diamini oleh Ardi. “Kita juga gak bisa naif,” timpalnya. “Mereka (para pengelola gedung) juga perlu dana untuk merawat bangunan itu.” Yang dihasilkan adalah sebuah proses tarik ulur antara fungsi bisnis dan keterbukaan. Bisa jadi, memang perusahaan dan bisnis lebih mampu mengelola dan merawat ruang tersebut. Resikonya, sebagaimana lokasi bisnis manapun, keterbukaan ruang tersebut tergantung pada keuntungan bisnis yang bisa didapat pengelola. Kompetensi pengelolaan negara yang masih diragukan membuat persoalan semakin rumit. “Misalnya mereka bilang Gedung Arsip mau dijadikan ruang publik bagi acara seni dan budaya,” ujar Ardi. “Publik mana yang mereka maksud? Seni dan budaya apa yang mereka maksud? Acara seperti apa? Kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak paham seni, malah jadi kacau.”
Memang, wacana ini tak berujung pada konklusi yang pasti. Malah, ia memantik lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Tapi, saya justru merasa inilah yang diinginkan para kurator. Pameran ini ingin mengajak pengunjungnya untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih kritis, alih-alih sekedar memberhalakan masa lalu dalam rangka merayakan konsep kejayaan yang seolah-olah akan datang kembali secara otomatis. Misalnya, mereka tak segan menjelaskan pada pengunjung tentang adanya riset baru – 10 tahun setelah konservasi rumah Schoemaker diganjar penghargaan – yang meragukan bahwa rumah di jalan Sawunggaling tersebut memang milik Schoemaker. Ini jelas lebih menarik daripada sekedar menyajikan kisah-kisah konservasi tersebut sebagai motivasi satu arah yang picisan.
Sayangnya, pameran tersebut pun penuh dengan keterbatasan. Menurut Ardi dan Robin, mereka hanya mendapat waktu sekitar 1,5 bulan dari UNESCO untuk mempersiapkan pameran tersebut – mulai dari riset sejarah dan visual, penulisan teks, hingga desain produksi. Jelas, keterbatasan waktu ini memaksa mereka untuk memangkas skala pameran dari rencana awal yang cukup ambisius. Ruang pameran di Gedung Jasindo yang terbilang kecil dan terlalu terbuka pun mengganggu pameran tersebut. Kerja keras tim desain produksi tentu patut diapresiasi, namun ruang pameran tersebut masih saja terasa sempit. Tak ada ruang yang cukup untuk benar-benar memamerkan kisah dari masing-masing situs secara mendalam. Yang membuat saya gemas, sebenarnya tersedia ruangan yang cukup luas tak jauh dari ruang pameran. Namun, ruangan tersebut malah digunakan untuk stand-stand pameran.
Kebisingan lokasi juga berpengaruh. Banyak suara dari luar – kerumunan yang ramai, arak-arakan Ondel-Ondel, hingga musisi jalanan – terdengar jelas di ruang pameran. Robin menjelaskan pada saya tentang rencana awal mereka untuk menyajikan data dan teks tersebut bersama rekaman audio dari daerah sekitar situs-situs tersebut. Jika saja ide ini berhasil dilaksanakan (dan menurut Ardi, ambient sounds ini sudah sempat direkam), maka pameran ini akan benar-benar jadi pengalaman audiovisual yang lebih lengkap. Secara pribadi, saya pun geleng-geleng kepala mendengar waktu persiapan yang diberikan UNESCO. “Gue gak bilang bahwa 1,5 bulan adalah waktu yang ideal untuk mempersiapkan pameran, atau bahwa lo bisa kok bikin pameran dalam waktu segitu,” ucap Ardi pada para peserta lokakarya. “Gue cuma ingin menunjukkan bahwa dengan waktu yang disediakan, lo perlu memikirkan kembali rencana awal lo. Coba lo hitung – apakah itu mungkin dilakukan dalam 1 bulan?” Lebih baik bersikap realistis, pesannya, ketimbang harus berakhir dengan terlalu banyak elemen rumit yang sama-sama belum matang dan malah merepotkan.
Terlepas dari keterbatasan yang mengganggu eksekusi ide mereka, Kisah Konservasi tetap membuat saya tertarik untuk, setidaknya, menghabiskan waktu dan membaca secara lengkap kisah dari kelima situs yang dikonservasi. Pameran ini menyingkap cerita-cerita sejarah dan narasi pribadi di balik usaha konservasi, dan menyorot inisiatif para arsitek, warga, dan kolektif independen yang tergerak dan bergerak untuk menyelamatkan situs-situs tersebut tanpa perlu disokong pemerintah.
Saat rombongan kami kembali ke bis dan beranjak keluar dari daerah Kota Tua, mata kami terpaku pada gedung-gedung tua lain yang masih tak terurus. Dinding-dinding yang retak, cat yang mengelupas, dan rerumputan liar memenuhi pandangan kami. Museum Fatahillah masih tertutup untuk umum, disembunyikan dengan kain penutup raksasa. Banyak pekerja masih berseliweran dekat Gedung Jasindo, mereparasi bangunan-bangunan tua yang nyaris runtuh di kompleks Kota Tua, satu per satu. Saya menutup mata saat kami melaju masuk tol. Mungkin suatu saat nanti, kita akan melihat Kota Tua dan tergerak untuk mengapresiasi masa lalu kita, alih-alih diingatkan pada sebentuk kejayaan lama yang telah pudar.
Lebih baik sekarang, daripada tidak sama sekali.
Dokumentasi: DKJ – Eva Tobing