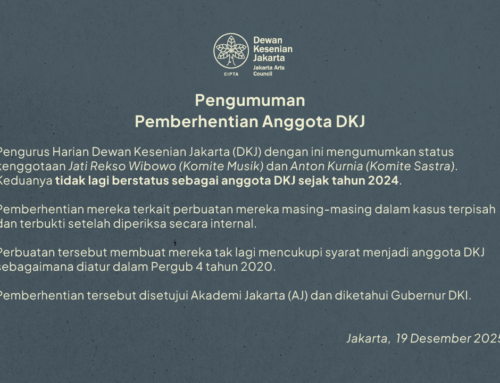Siapa yang tak kenal Pramoedya Ananta Toer? Sosok penyulam kata yang karyanya lahir dari luka, keberanian, sekaligus cinta yang getir pada Tanah Air. Bahasanya bukan sekadar alat untuk bercerita, melainkan senjata, mengupas lapis-lapis kenyataan sosial dan politik, hingga pembaca terperangkap dalam arus sejarah yang terasa begitu hidup.
Fakta dan fiksi disulam dengan apik dan menghadirkan tokoh-tokoh yang bukan hanya berdiri sebagai karakter, melainkan sebagai jiwa-jiwa zaman, cermin kolektif dari bangsa yang sedang mencari dirinya.
Pram –begitu dia disapa– menyusuri kajian arsip dan riset sejarah yang lekat pada tema di dalam karyanya. Tak heran jika karya-karya Pram memberi warna unik dalam sejarah sastra di Indonesia–seperti kisah Hardo yang mendapatkan penghargaan sayembara oleh Balai Pustaka dalam novel Perburuan (1950), Hoakiau di Indonesia (1960) yang menjadi kritik akan diskriminasi terhadap Tionghoa, hingga perjuangan tokoh Minke dalam membangkitkan nasionalisme Indonesia dalam Tetralogi Buru.
Jejak langkahnya dalam kesusastraan Indonesia membuat Pram menjadi sosok yang diakui baik nasional maupun internasional. PEN International sebuah asosiasi untuk penulis dan sastrawan di dunia menghargai Pram sebagai anggota kehormatan pada acaranya yang ke-8.
Seabad Pram
Pada 6 Februari 2025 lalu, diperingati sebagai 100 tahun lahirnya Pram. Dalam rangka mengenang seabad Pram dan kiprahnya pada sastra Indonesia, Komite Sastra bekerja sama dengan Komisi Simpul Seni Dewan Kesenian Jakarta melangsungkan program Membaca Pram yang berlangsung sepanjang April hingga November.
Sepanjang Juni lalu, tepatnya pada 6, 13, 20, dan 27 Juni 2025 di Taman Ismail Marzuki, Membaca Pram mengadakan pemaparan hasil riset yang dilakukan semenjak April oleh peserta yang dipandu oleh Zen Rachmat Sugito atau Zen RS dengan mengajak pembaca menjejaki karya-karya nonfiksi Pram.
Seabad Pramoedya Ananta Toer: Membaca Pram, bertujuan untuk melestarikan dan memberi apresiasi terhadap karya Pram yang sekiranya tetap relevan pada sosial, budaya, serta politik kontemporer. Membaca Pram mengajak peserta berpartisipasi dalam menelisik serta mengkritisi kembali torehan kata-kata Pram dalam narasinya yang tetap progresif dalam perkembangan sastra Indonesia.
Gelaran acara ini dibuka dengan peserta membaca ulang dan melakukan riset pada penulisan Pram baik fiksi dan nonfiksi, serta berusaha melihat keterhubungan antar-keduanya sebelum melakukan pemaparan hasil secara offline di ruang S. Rukiah Kertapati, Taman Ismail Marzuki. Pada saat pemaparan hasil riset, peserta diminta untuk sama-sama membuka diskusi memberi masukan serta perspektif baru akan bacaan ulang terhadap karya Pram. Zen RS terlibat dalam memberikan masukan bagi peserta terutama dalam perbaikan penulisan dan memandu keterbukaan pandangan dalam diskusi.
Peserta memberikan pemaparan melalui hasil bacaan dari karya Pram di antaranya Perburuan (1950), Realisme-Sosialis dan Sastra Indonesia (1956), Hoakiau di Indonesia (1960), Gadis Pantai (1962), Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer (1979), Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1988), Kronik Revolusi Indonesia (1999), Sang Pemula (2003), dan Jalan Raya Pos, Jalan Daendels (2005).
Pada poin penekanan yang diberikan oleh Zen RS dan Dewan Kesenian Jakarta, salah satu tema yang dapat ditelaah adalah Gerakan Sosial, Minoritas, dan Kewarganegaraan. Elen Yulance Y, salah satu peserta yang mengikuti Membaca Pram, membawakan pemaparan bertajuk, Pram dan Perempuan: Melawan Subordinasi. Dalam pembacaannya, Elen menekankan pada subordinasi serta emansipasi terhadap perempuan. Dirinya memberikan hasil pembacaan salah satunya dari Gadis Pantai (1962) yang dikutipnya melalui percakapan yang dilakukan Bendoro, salah satu karakter dalam novel tersebut. Tema ini menelisik lebih dalam akan marginalisasi dan struktur sosial yang ada pada masyarakat.
Tema lain yang juga diusung dalam Membaca Pram antara lain: Kolonialisme, Kebangsaan, dan Lahirnya Nasionalisme; Revolusi dan Memori Kolektif; Tradisi Lisan dan Sejarah Rakyat; serta Pengasingan dan Produksi Pengetahuan–sebuah langkah dalam menyusuri warisan bangsa dan semangat perjuangan dalam membangun ingatan bersama di masyarakat dulu, kini, dan sekarang.
Pemaparan yang dilakukan oleh peserta saat ini sedang menuju proses penerbitan yang diperkirakan selesai pada September. Perspektif yang hadir dalam Membaca Pram juga menjejaki diskusi-diskusi lanjutan di ruang publik bersama komunitas lain yang akan berlangsung di bulan November. Diskusi publik akan terjadi di Teater Wahyu Sihombing serta ruang komunitas seperti Makarya, Atelir Ceremai, POST Santa, TB Balzac, TB Bebasari, dalam memperluas jangkauan sudut pandang pembaca terhadap sosok Pramoedya Ananta Toer.
Seabad Pramoedya Ananta Toer: Membaca Pram membuka sudut pandang akan pembacaan Pram yang menarasikan hiruk pikuk kehidupan bangsa Indonesia dari penjajahan serta perjuangan untuk keluar darinya. Nama Pramoedya Ananta Toer sebagai seorang sastrawan, pejuang, bahkan jurnalis menghidupkan eksistensi dan warisan intelektual serta sastra di Indonesia. Relevansi dari torehan kata-katanya juga tetap hidup membangun kebebasan berpikir, keadilan, serta keberpihakan terhadap kelompok marjinal dalam hidup sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia.
(Marcelina Elenora Terainconita Tukan)