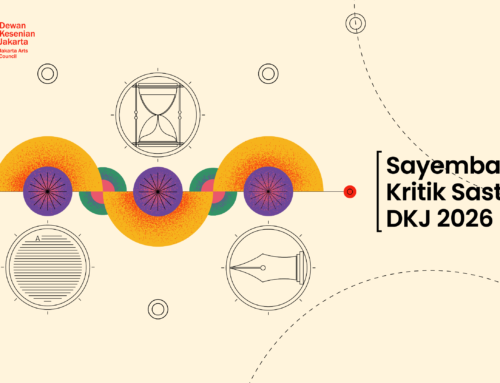Seperti juga kegiatan Lampion Sastra yang digelar setiap bulannya di Sanggar Baru, pembacaan cerpen-cerpen karya para sastrawan mumpuni tahun 50an, 13 April 2007 yang lalu ini meneteskan titik-titik kesegaran. Bagi orang yang awam sama sekali barangkali mendengar judulnya akan membuat dahi sedikit berkerut, dengan persepsi ‘wah… bakalan berat isinya’, ternyata semua itu menjadi ringan dan terkadang gelak tawa. Memang… si pembaca cerita memang harus pandai-pandai membawakan kisahnya.
Sebuah layar putih malatarbelakanginya, panggung pun di set untuk memperkuat unsur masa 50an. Sepeda ontel, mesin tik tua, bangku kayu di atas satu undakan hitam-putih yang mewakili sebuah lantai, pembaca cerita pun berpenampilan sangat kerakyatan. Epi Kusniar membuka acara dengan membaca ‘Robohnya Surau Kami’ karangan Ali Akbar Navis atau biasa disebut A.A. Navis.
Kisah Ajo Sidi dalam ‘Robohnya Surau Kami ini’ adalah seorang pembual yang hobi mengarang-ngarang cerita dengan tokoh-tokoh yang sedikit banyak identik dengan orang-orang di sekitarnya. Urusan cerita-bercerita ini ternyata membuat geram seorang kakek. Ia yang hidupnya selalu berserah diri kepada Yang Maha Esa, mengingatkan masuknya waktu sholat lewat pukulan beduknya dan tak pernah ingin menyakiti seekor lalat pun, dikatakan sebagai manusia terkutuk. Dalam bualan Ajo Sidi, orang-orang yang hanya menyembah kepada Yang Maha Esa dan menelantarkan keluarga, tak beramal, menyia-nyiakan kesuburan tanah yang diberikannya bakal jadi penghuni neraka. Rupanya kisah itu sangat merasuk hati sang kakek, yang pada akhirnya silet pun berbicara… ia pun menggork lehernya sendiri.
Mimik, artikulasi dan olah tubuh Epi Kusniar cukup baik. Sebagai aktor yang berpengalaman, pembawaan Epi pun cukup ekspresif dan terkadang bodor. Gelak tawa pun menyelingi dari penonton yang asyik duduk di lantai beralas tikar. Bahkan sejumlah anak-anak SMA Kanisius, SMA 35 dan 107 yang datang mendapatkan hiburan yang berbeda. Pada saat rehat Adzan Maghrib, Yuniarti bersama teman-temannya dari SMA 107 menikmati kisah Ajo Sidi,”Kita datang karena Pak Savenus, Pembina teater di sekolah dapat undangan. Melihat acara ini bisa jadi inspirasi dan tahu berbagai karakter pada saat kita saat pentas teater. Kadang-kadang cerita dibuat sendiri, tapi kalau untuk lomba kita ambil dari novel.”
Usai Adzan Maghrib, giliran Iman Soleh naik ke panggung. Dengan gayanya seperti Abang Jampang Jago Betawi, ia pun mulai membawakan “Sunat” cerpen yang ditulis Pramoedya Ananta Toer. Berbeda dengan anak-anak sekarang yang suka cari dalih saat mengaji, maka kisah ini justru mengaji adalah kesempatan untuk tidak belajar di malam hari. Tentu saja ngaji di benak anak-anak dari Pram ini adalah untuk bermain dan canda tawa. Usia 9 tahun adalah masa-masa menjalani ritual sunat. Keberanian untuk sunat selalu menjadi kebanggan sang kyai, karena ia mengatakan sang anak akan ditemani empat puluh empat bidadari. Sementara di mata anak melalui karakter ‘Aku’ menganggap dengan bersunat berarti jatah masuk surga pun di dapatkannya. Ia justru tak ingin dengan banyaknya bidadari. “Tapi aku tak suka pada bidadari yang teteknya enam atau delapan seperti anjing,” ujar Aku kepada sang kyai. Gelak tawa Kyai pun menggema… seperti juga gema para penonton yang melanjutkan acara Lampion Sastra yang mulai temaram.