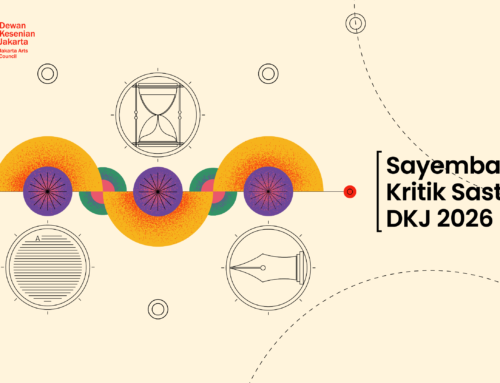“Yang menggembirakan adalah bahwa di luar naskah yang masuk itu masih sangat banyak sajak yang ditulis oleh penyair yang, entah karena apa, tidak memasukkan sajak-sajaknya untuk sayembara penulisan ini.”
Begitu salah satu catatan dewan juri sayembara puisi Dewan Kesenian Jakarta saat terakhir kali kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2001, empat belas tahun yang lalu. Kenyataan tersebut belum banyak berubah. Lima ratus tujuh puluh dua manuskrip masuk dalam “Sayembara Manuskrip Buku Puisi DKJ 2015”, dan itu baru sebagian kecil dari puisi yang kita tahu dibuat, diedarkan, dan kadang-kadang dibaca di seantero negeri ini.
Jumlah 572 manuskrip buku puisi yang mengikuti sayembara ini menunjukkan bahwa puisi masih merupakan genre sastra yang sangat populer dan kegairahan menulis puisi seakan tiada habisnya. Namun, sayangnya, kami ternyata sulit mendapatkan manuskrip-manuskrip yang menawarkan kesegaran, baik dalam hal tema maupun cara pengucapan; yang bisa memperluas wawasan kita mengenai puisi dan cara berpuisi. Sebagian besar manuskrip terbenam dalam keumumam, kelampauan, dan keusangan dan sulit menemukan jalan pembebasan.
Agaknya masih banyak penyair yang meyakini bahwa puisi adalah tempat paling nyaman untuk curhat. Tidak mengherankan, banyak manuskrip yang oleh para penulisnya diperlakukan sebagai semacam tempat pembuangan bagi tumpahan perasaan pribadi si aku penyair beserta kata-kata mentah yang belum diolah dengan nalar dan imajinasi.
Sebaliknya, satu lagi kecenderungan menonjol dari peserta Sayembara Manuskrip Buku Puisi DKJ tahun ini adalah hasrat berlebihan untuk berindah-indah dengan bahasa. Hasilnya adalah puisi yang banyak mendemonstrasikan kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang manis, gagah, mentereng, penuh akrobat bahasa, yang sayangnya tidak membawa kita menuju kejernihan, melainkan kerumitan dan keruwetan; yang tidak mengantar kita ke dunia terang, melainkan malah makin membenamkan kita ke dunia gelap yang penulisnya sendiri pun belum tentu dapat memasukinya. Anggapan bahwa puisi adalah karya yang disusun dari kata-kata yang indah secara negatif dapat menjebak penyair pada kecenderungan menulis karya yang berlumuran bedak dan lipstik, penuh bunga dan busa, namun majal, hampa makna, dan kehilangan kewajarannya.
Salah satu tahap penting dalam proses penulisan puisi adalah seleksi kata. Tahap ini tampaknya telah diabaikan oleh banyak penyair. Seleksi kata: memilih kata-kata, imaji-imaji, unsur-unsur yang relevan. Entah karena penulisnya kurang percaya dengan kemampuan pembaca, entah karena mereka tidak mampu mengontrol kata-kata, banyak puisi yang kedodoran, mubazir, sesak napas, kelebihan muatan kata-kata karena penulisnya ingin mengatakan dan menjejalkan terlalu banyak hal dalam ruang yang terbatas. Puisi bukan hanya menjadi sumpek dan pengap, tidak memberikan ruang pemaknaan, melainkan juga kehilangan fokus sehingga tidak jelas maunya apa. Itulah puisi yang terlalu banyak berkata-kata hanya untuk tidak mengatakan apa-apa.
Seorang penulis puisi tentu saja mesti membereskan dirinya dalam hal kemampuan berbahasa tulis dengan baik. Berbagai error berbahasa, termasuk kerancuan logika, dalam banyak manuskrip jelas tidak berkaitan dengan licentia poetica. Error yang kami jumpai bahkan menyangkut perkara teknis yang sangat elementer, misalnya ejaan dan tata tulis. Sekadar contoh, masih banyak yang tidak dapat membedakan awalan di- dengan kata depan di.
Ada cukup banyak manuskrip yang berisi puisi-puisi bertema sosial. Sayang sekali, puisi-puisi itu masih mentah dan berhenti sebagai jargon, luapan emosi, atau liputan sosial-politik yang dapat dengan mudah kita temukan dalam berita-berita di media massa. Cukup banyak juga manuskrip yang menggali unsur-unsur lokal. Masalahnya, unsur-unsur lokal tersebut cenderung menjadi eksklusif, tidak terdeskripsikan dan terterjemahkan dengan baik dan memadai sehingga menghambat dan mempersulit pemaknaan.
Ada catatan yang patut dipertimbangkan dalam menilai arti “Sayembara Manuskrip Buku Puisi DKJ 2015”. Memang dewan juri berusaha untuk mencari manuskrip yang menawarkan kekuatan tema, kebaruan, dan teknik menulis yang mantap, namun harus diingat bahwa sayembara ini tidak melakukan scouting untuk mencari manuskrip puisi yang dianggap ideal, hanya menggantungkan diri kepada naskah yang masuk. Jadi, hasil sayembara ini sebaiknya dilihat bukan sebagai sebuah “keputusan pengadilan” tentang kebaik-burukan dunia puisi Indonesia, namun sebagai refleksi dari sebagian saja kecenderungan puisi kontemporer Indonesia.
Dengan catatan tersebut, kabar gembira masih menghampiri kami. Tiga manuskrip yang kami tetapkan sebagai pemenang menunjukkan teknik penulisan yang matang dengan gaya yang berbeda-beda, intertekstualitas yang matang sebagai strategi untuk mengatasi mimikri dan mengekploitasi hibriditas identitas mereka, serta keberanian mengekplorasi tema-tema yang jarang digali penyair-penyair lain, dulu maupun sekarang, baik itu karena temanya sering dianggap terlalu banal atau malah terlalu kontroversial.
Salah satu dari manuskrip tersebut, dengan bahasa yang simpel, berhasil memotret kekompleksan kehidupan domestik bagi seorang ibu di Indonesia. Manuskrip ini bercerita tentang tetek-bengek urusan rumah secara literal, sekaligus rumah sebagai metafora tubuh dan jiwa seorang ibu yang dikacaubalaukan oleh pengalaman melahirkan dan membesarkan anak. Ending di puisi-puisi dalam manuskrip ini seringkali menakjubkan, menyulap detil-detil banal kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu yang hampir sureal. Manuskrip ini, nomor 422, “Ibu Mendulang, Anak Berlari: Kumpulan Puisi Pendek di Atas Celemek” karya Cyntha Hariadi, kami pilih sebagai Juara Ketiga.
Manuskrip berikutnya menunjukkan penyairnya dapat menyerap dengan baik gaya berpuisi para penyair terdahulu seraya mengembangkannya menjadi lebih luwes dan variatif dengan konteks yang lebih luas. Ia membiarkan alusi menjadi alusi, tidak ketakutan kemudian menjadikannya sekedar catatan kaki, atau malah tergoda menjadikannya bahan pamer. Di sana-sini juga muncul empati sosial yang dideskripsikan dengan lembut. Pengendapan emosi, intensitas, dan kesubliman merupakan kekuatan manuskrip ini di samping kemampuan berbahasa yang baik. Manuskrip ini, nomor 314, “Kawitan” karya Ni Made Purnama Sari, kami tetapkan sebagai Juara Kedua.
Manuskrip yang kami tetapkan sebagai Juara Pertama adalah naskah yang sangat mengharukan. Naskah ini menghadirkan tema yang jarang diolah secara demikian baik dalam puisi Indonesia: kehidupan dan identitas homoseksual (juga, lewat narator yang kadang lelaki kadang perempuan, identitas transgender). Puisi-puisi dalam manuskrip ini melukiskan—kadang lewat gaya pengakuan pseudo-memoir, kadang lewat kode-kode literer yang bakal memerlukan detektif sastra untuk memecahkannya—kegalauan batin tokoh yang sedang bertanya-jawab mengenai identitas dirinya, yang dianggap sebagai liyan oleh keluarga dan lingkungan masyarakat serta budayanya. Di beberapa poin, tanya-jawab ini menembus dimensi spiritual yang mengejutkan. Tidak seperti kecenderungan banyak intelektual Indonesia masa kini, kumpulan puisi ini tidak mereduksi agama menjadi sesuatu yang irasional, kemudian melepehkannya. Penyairnya justru seperti sedang mencari cara untuk paling tidak bersahabat dengan tuhannya.
Walaupun manuskrip ini menceritakan sebuah tragedi, kisah-kisahnya disampaikan dengan nada ringan, nyaris komikal (bahkan ada beberapa pastiche ala puisi mbeling), yang justru membuat ceritanya makin tragis. Pemakaian ironi yang mantap! Selain itu, penulis juga menunjukkan kepiawaiannya mencampuraduk berbagai macam referensi, alusi, dan gaya. Dari yang kuno sampai yang kekinian, dari high culture sampai ke pop culture. Sering referensi-referensi ini menunjukkan bukti telah dipertimbangkan dengan matang untuk menjadi semacam hyperlink yang memberikan petunjuk sekaligus kedalaman lebih lanjut tentang tema kegalauan identitas homoseksual dan transgendernya. Manuskrip nomor 78 ini, “Sergius Mencari Bacchus” (sebagai salah satu bukti pemilihan referensi yang matang tadi, Santo Sergius dan Bacchus adalah martir dari abad ke-4 yang karena persahabatan mereka yang erat sering diadopsi sebagai gay icons) bisa jadi akan membuka jalan bagi puisi dan penyair serupa setelahnya. Penulisnya telah menghadirkan satu problem dan situasi kontemporer yang pelik dan jarang disentuh oleh penyair lain lewat kemasan yang juga sangat kekinian dalam intertekstualitasnya. “Sergius Mencari Bacchus” paling menjawab keinginan kami untuk menemukan naskah yang menawarkan tema kuat, kebaruan, dan teknik penulisan yang segar dan mumpuni. Karena itulah kami memilih naskah karya Norman Erikson Pasaribu ini sebagai yang terbaik.
Ketiga manuskrip pemenang sayembara ini adalah refleksi dari kemampuan puisi Indonesia untuk tetap bertahan, beregenerasi, dan berevolusi.
Dewan Juri Sayembara Manuskrip Buku Puisi Dewan Kesenian Jakarta 2015
Oka Rusmini
Joko Pinurbo
Mikael Johani