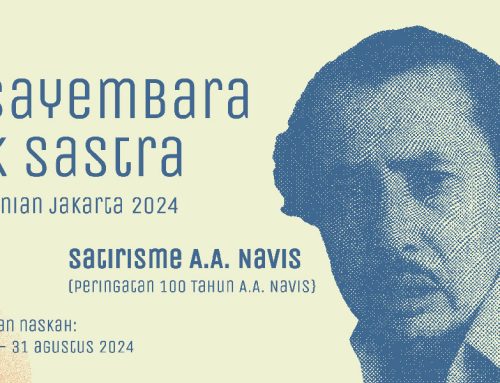Catatan Ags. Arya Dipayana untuk pertunjukan Ditunggu Dogot karya Sapardi Djoko Damono yang disutradarai Kurniasih Zaitun, produksi Komunitas Hitam Putih.
Waktu : 27 Juli 2007, pukul 20.00
Tempat : Sanggar Baru, Taman Ismail Marzuki, Cikini Jakarta Pusat
Ditunggu Dogot merupakan pertunjukan teater yang mengangkat cerita pendek karya Sapardi Djoko Damono sebagai titik tolaknya. Dari pilihan judul, pengarangnya secara sadar menginformasikan bahwa cerpen tersebut memiliki korelasi dengan naskah drama karya Samuel Beckett, Menunggu Godot. Apa yang membedakan dua karya tersebut adalah bahwa Samuel Beckett menempatkan manusia dalam posisi pasif yaitu menunggu, sedang Sapardi Djoko Damono menempatkan manusia dalam posisi yang dituntut untuk aktif, sebagai konsekuensi logis dari pihak yang ditunggu.
Dalam sinopsis yang dibagikan kepada penonton, tertulis bahwa Ditunggu Godot mengungkapkan perjalanan dua orang tokoh, laki-laki dan perempuan yang sedang ditunggu Dogot. Dalam perjalanan mereka terlibat dalam dialog dan konflik tentang urgensi perjalanan mereka. Dalam perdebatan tersebut terlintas pernyataan bahwa apa dan siapa Dogot menjadi tidak penting, sekurangnya dibanding usaha yang harus segera dijalankan untuk sampai di tempat pada waktu yang tepat.
Komunitas Hitam Putih menawarkan bentuk pemanggungan yang tidak biasa, yaitu dengan mengambil konsep stage on stage (panggung di atas panggung). Di atas panggung – dalam arti bidang atau ruang yang tetap — dihadirkan panggung lain yang dapat bergerak (berputar). Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pendekatan un-blocking, di mana pergulatan di atas panggung tidak hanya ditentukan oleh movement para pemain, melainkan terutama oleh perputaran panggung.
Property utama dari pertunjukan ini adalah sebuah sepeda kayuh yang ditempatkan di tengah-tengah panggung. Dua orang pemain yang terdiri dari tokoh Laki-laki (Rudyaso) dan Perempuan (Eliza) berkutat dengan kemungkinan visual menggunakan sepeda tersebut, dalam upaya menyaran pada perjalanan. Di bagian belakang panggung dipasang layar untuk tayangan multimedia, dalam rangka mencapai atmosfir dramatik dari suatu perjalanan yang amat jauh, berliku-liku dan melelahkan.
Pertunjukan ini sangat menarik dari konsep pemanggungan dan visual pertunjukan. Dimainkan selama kurang-lebih 60 menit, penonton disuguhi oleh perubahan visual yang kaya, diantar untuk mencapai imaji dari pergulatan para pemain dengan cara yang sensasional dan tak terduga. Sayang sekali bahwa para pemain masih memiliki kendala dengan penguasaan teknik pemeranan, sehingga dialog – yang seharusnya terasa dalam, sulit dan pelik – menjadi sekedar hapalan yang tidak mengisyaratkan makna apa-apa.
Mencermati pertunjukan dari awal hingga akhir, terkesan bahwa sutradara lebih asyik untuk menjelajahi berbagai kemungkinan bentuk ketimbang mengantar para pemain untuk sampai pada capaian tertentu dalam pemeranannya. Alhasil, esensi dari pertunjukan menjadi kabur oleh permainan yang monoton dan tidak berjiwa. Hal ini juga nampak dari komentar dan kritik penonton dalam diskusi sehabis pertunjukan, yang dihadiri oleh cukup banyak pekerja dan tokoh-tokoh teater Jakarta. Tentu saja tanpa menutup kenyataan bahwa Komunitas Hitam Putih telah berhasil memberi suguhan yang cukup segar dan inspiratif.
Patut dicatat bahwa pertunjukan ini menggunakan konsep pemanggungan yang merupakan adaptasi dari pola teater randai dari Minangkabau. Hal ini diwujudkan dengan menempatkan unsur galombang dan pelaku galombang sebagai faktor yang menentukan, bukan saja pergantian waktu dan tempat, bahkan barangkali juga nasib manusia. Sebuah upaya mengaktualisasi khasanah tradisi yang banyak dilakukan orang, dengan amat sedikit yang berhasil mencapai. Kurniasih Zaitun salah satu dari yang sedikit itu.